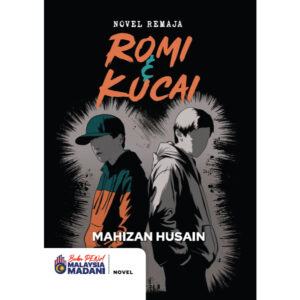NANA meriba bayi yang baru dilahirkannya. Terasa megah kerana buat kali pertama bergelar ibu. Penantian bertahun-tahun berakhir apabila dia membawa seorang putera ke dunia ini. Kebahagiaannya berganda kerana kini dia masih berada di persekitaran yang menjadikan dia siapa dirinya – seorang wanita dari suku Bisaya – dilahirkan dan kini, membawa seorang putera suku Bisaya pula di tanah tumpah darahnya. Pengalaman pertama melahirkan puteranya berserta kenangan terindah mendengar tangisan pertama mengiringi azan iqamat yang dilaungkan ke telinga anaknya.
“Bertuahnya sayang mama, mendengar iqamat yang dilaungkan sendiri oleh aki Arif,” bisik Nana, mengucup pipi bayinya yang berbau segar dan wangi.
“Sudah-sudahlah, kak,” rungut Nina.
Nana menjawab dengan senyum lebarnya. “Apa salahnya, kan sayang?” Nana mencuit pipi bayinya sambil ketawa gembira.
“Ada masalahkah? Muka monyok macam ayam berak kapur ini…”
“Aku bengang dengan sikap anak saudara kakak itu.”
“Siapa?”
“Faridlah, siapa lagi?”
“Sebabnya?”
“Pasal Ladang Karamislah, apa lagi…”
“Masih rasa ralatkah tentang cadangan membuka ladang ternak baharu yang dibangkitkan oleh Haji Rahman tempoh hari?”
“Ya. Aku paling tidak gemar dengan isu pembangunan yang sering dipolitikkan. Aku tahulah mereka itu rajin mencari bahan tercemar untuk dibawa ke tengah. Tapi aku malu dengan sikap mereka yang mencemarkan air muka kami yang lebih dahulu merasa masin garam daripada mereka,” Nina berhujah semakin berapi-api. Dia geram dengan sikap anak buahnya yang langsung tidak mengumpamakan dengan siapa dia berbicara. Hujah dilontar mengikut sedap mulut sahaja. Tanpa mengkaji hati siapa yang bakal tergores.
“Ah, biarkanlah dia. Kita semua ada hak untuk menyuarakan pendapat masing-masing. Kita ini hanyalah mentimun…” ucap Nana, meredakan marah adiknya.
“Masalahnya mereka itu hanya mengambil rumusan masing-masing dan selepas itu cuba pula menghasut orang lain untuk menyebelahi mereka. Aku terserempak dengan Farid di gerai minum Abang Syahir, sedang menghuraikan dakyahnya. Pendengarnya pula terangguk-angguk seperti burung belatuk. Main tangkap muat sahaja.”
“Jadi? Kau ada menyampuk perbahasan mereka?” soal Nana, masak benar akan sikap degil adiknya itu.
“Seperti biasalah. Aku bubuhlah asam pedas secukup rasa ke telinga mereka…” akui Nina dengan pandangan bersalah ke arah kakaknya.
Nana tersengih. Terasa lucu. Adiknya memang begitu. Suka main lepas cakap sahaja. Berkali-kali Nana mengingatkannya supaya menjaga mulutnya agar tidak celopar dan tidak menyinggung perasaan orang lain.
“Bila bercakap, berpada-pada. Kalau tidak buruk padahnya…” nasihat Nana kepada adiknya yang kepala angin itu. Namun nasihatnya sering berlalu sepi, seperti mencurah air ke daun keladi.
Isu mengenai cadangan pembukaan ladang ternak baharu di Ladang Karamis telah diusulkan dan sedang dibahaskan di seluruh jajahan Kampung Hulu. Keluarga Nana tidak terlepas daripada membahaskan isu hangat itu. Beberapa hari selepas perbincangan Nana dan Nina, Farid singgah menjenguk. Selepas berbasa-basi, perbualan mereka mulai beralih ke arah isu panas ketika itu.
“Aku dengar bukan main lagi kamu mengutuk Haji Rahman? Apa masalah kamu sehingga tidak puas hati dengan dia?” Nina membuka mukadimah.
“Aku tidak berminat membincangkan perkara ini. Pendapat kami bukannya diterima. Kami ini telah dilabelkan sebagai pembangkang…” jawab Farid seolah-olah merajuk.
Nana mencuri pandang ke wajah Nina dan Farid. Dia berasakan udara hangat dan kurang menyenangkan sedang berlegar di ruangan itu. Hatinya berkalih tidak selesa.
“Bukan tidak terima. Tetapi fahaman kamu itu terlalu menghukum. Kalaupun kamu tidak setuju, salurkanlah kepada pihak berkenaan,” balas Nina, melarikan pandangannya dari muka Farid.
“Saluran mana, unsu? Tok ketua? AJK kampung? Semua pun sama satu kepala…” rungut Farid, mengumpat secara terbuka.
Wajah Nina berubah keruh. “Kamu yang muda ini memang tidak tahu cara menghormati orang tua. Bagaimana kamu mengharapkan suara kamu didengari kalau kamu semua malas ambil tahu? Diajak bermesyuarat, kamu tidak pernah hadir. Kamu inginkan kemajuan tapi tidak pernah mahu menyumbang tenaga dan idea. Asyik mengguna pakai otak tua. Jadi, kamu tiada hak untuk merungut sebab kamu tidak pernah ada masa untuk berbincang,” balas Nina. Nadanya sudah berubah semakin dingin dan berbau sinis. Mungkin angin sedang berdesir di atas ubun-ubun kepalanya ketika itu.
“Itulah kamu yang berjawatan tinggi! Ajak mesyuarat ikut sedap kamu saja. Orang lain ini perlu bekerja, mencari pengisi periuk nasi untuk anak isteri. Hantar surat pada saat-saat akhir, bagaimana orang senang hendak datang.”
“Kami sudah hafal dengan alasan-alasan basi begitu. Itulah saja yang diberikan berulang-ulang. Jadi, waktu bagaimana yang kamu inginkan? Yang ikut sedap perut kamu? Kalau begitu, terpaksalah kami buat mesyuarat untuk setiap seorang daripada kamu, bergantung pada waktu senggang masing-masing. Wah, kami tiada kehidupan peribadikah? Tiada kerja lain yang lebih berfaedah? JKKK ini sudah seumpama pengemis, kamu tahu tak? Mereka terpaksa mencari cara hingga ke tahap memberi imbalan kepada yang hadir untuk meramaikan majlis. Orang-orang sekarang ini bukannya hairan dengan kuih ataupun kopi yang dihidang. Kalau duit, berbaris panjang pun sanggup…” sindir Nina.
Air muka Farid berubah keruh. Melihat situasi tegang itu, Nana terpanggil untuk menyampuk pertelagahan dua beranak itu. Dia memandang wajah masam adik bongsunya dan wajah kelat anak buahnya silih berganti, mengulum rasa kesal di dadanya. Kalau dia tidak menyampuk, pertengkaran itu akan menjadi semakin serius, jika dilihat pada rona muka mereka berdua. Nina pun satu. Tidak tahu membahasakan rasa tidak puas hatinya dengan lebih lembut. Apabila dua kuasa berlaga, tentu percikan api akan bersimbahan ke permukaan.
“Kamu berdua ini tidak saling berpandang wajahkah? Kamu sedang berlaga dengan siapa ni?” soal Nana, meletakkan anaknya, Arif, ke dalam buaian. Bimbang nanti dia pula yang naik angin dan meroyan, melayani kerenah dua manusia sama degil di depannya.
“Aku memang tidak boleh terima sikap biadab…” jawab Nina dingin.
“Kamu berdua ini sama saja. Tidak dapatkah berbincang baik-baik?” soal Nana.
“Tiada gunanya berbincang dengan orang yang sombong bodoh. Bila bercakap, asyik hendak mendengar suara sendiri. Bagaimana dapat mendengar suara orang lain…”
“Farid! Kamu jangan melampau…” sergah Nina, mengejutkan Arif yang berada dalam buai. Untuk seketika, suasana hening barusan kini dipecahkan oleh suara tangisan Arif memekakkan telinga mereka bertiga. Setelah memujuk anaknya, akhirnya bayi itu tidur semula.
“Baik, sekarang cuba kamu terangkan di manakah letaknya masalah kamu berdua ini?” soal Nana dengan geram.
“Kami ahli JKKK tiada masalah untuk menerima dan menyokong cadangan Haji Rahman untuk memajukan Ladang Karamis. Tetapi nampaknya ramai dalam kalangan anak muda tidak bersetuju dengan cadangan itu. Mereka menuduh Haji Rahman menipu duit penduduk kampung. Tuduh dia mengambil kesempatan mengaut keuntungan untuk diri sendiri sedangkan kita ada koperasi. Ada pula yang menuduhnya menggalakkan perjudian dengan mengadakan pelbagai pertandingan dan temasya,” jelas Nina dengan sugul.
“Memanglah kami tidak berpuas hati. Tanah Ladang Karamis itu tanah rizab untuk karabau. Tanah nenek moyang kita. Bukannya tanah persendirian. Pelbagai projek ada disebutkan untuk dibina di situ, tetapi tempat itu masih lagi hutan tebal. Kalaulah jadi mereka membina kedai koperasi di situ, adakah pembelinya? Sudahlah jauh di tengah hutan. Kalau kedai muflis, kita dapat tempiasnya. Apa tidaknya kalau koperasi tiada keuntungan, bagaimana kita hendak mendapatkan dividen?” Farid terus merungut.
“Jadi, yang kamu berdua hendak beritahu aku sekarang ialah, kamu saling mempertahankan perkara yang kamu rasa betullah, kan?” soal Nana, menghela nafas berat.
Nana mula nampak polanya. Ia tentang dua perbezaan idea yang dipegang oleh dua generasi. Nina contoh warga desa sebenar. Yang tinggal, hidup dan bernafas di desa mereka yang dulu sepi. Apabila kini pembangunan mula menjengah menjanjikan aroma kemajuan, dia menerimanya dengan tangan terbuka. Dia menyokong dan setia kepada pemimpin yang merintis jalan sukar itu.
Farid pula contoh generasi yang telah bergelumang dengan kemodenan. Mereka sudah tidak tertarik dengan janji yang terlalu lama untuk menggapainya. Mereka ini generasi ‘segera’. Semuanya hendak cepat.
‘Akibat terlalu menelan banyak makanan segera,’ fikir Nana separuh mengejek.
Antara Nina dan Farid, kedua-duanya alatan yang paling ampuh untuk melestarikan kemajuan dengan syarat, mereka harus mencari titik sentuhan yang boleh digunakan untuk merapatkan jurang pendapat daripada kedua-dua generasi dan di situlah masalah Nina dan Farid bertemu.
“Aku rasa, kamu berdua sama-sama betul dan sama-sama salah,” putus Nana. Dia dihunjam dengan sorot dua pasang mata tajam.
“Mak Cik Nana tidak faham apa-apa mengenai akar perselisihan ini…” balas Farid.
“Masalah kamu ini bukan perkara baharu. Memang dari dulu lagi kita amat payah untuk mencari kata sepakat. Sebabnya kita semua cuma hidup dengan separuh badan sahaja…” Nana memancing minat kedua-dua pihak. Nina dan Farid menunggu penjelasan daripadanya.
“Kita hidup hanya dengan separuh deria sahaja, itu sebabnya kita gagal untuk merasa. Ketika bertindak, kita tidak gunakan kepala kita. Tidak mendengar dengan baik, bagaimana otak boleh memproses maklumat dengan baik. Apabila membuat keputusan, ikut kata hati saja, bagaimana untuk bersikap bijak kalau tidak diimbangi dengan otak. Cuba kita kaji masalah ini daripada akar umbinya.” Nana menarik nafas.
“Masalah kita bermula daripada Ladang Karamis yang diteroka oleh nenek moyang kita. Bayangkan apakah yang mereka inginkan ketika mereka menebang pokok, meratakan tanah dan kemudian memutuskan untuk menjadikan tanah luas ini sebuah ladang karabau? Tentu mereka mengimpikan kemajuan untuk kita. Ketika itu, mereka tidak bodoh seperti kita… Mereka tidak bertengkar tentang hak. Mereka hanya membina, memagar, bergotong-royong tanpa gaji. Kalaulah mereka tahu cucu-cicit mereka bertelagah, saling mempersoalkan mengenai hak, tentu mereka kecewa dan lebih rela membiarkan hutan itu menjadi tempat jin beranak-pinak.” Nana melontar pandangan ke arah adik dan anak buahnya.
“Tentang tuduhan menipu itu, kenapa pula kamu yang sibuk menghukum Haji Rahman? Dia baik ataupun jahat, biar Allah yang tentukan. Menghukum bukan kerja kita. Itu kerja Allah.” Nasihat itu ditujukan kepada Farid.
Nana menoleh ke arah adiknya. “Selepas hidup di daerah orang yang jauh lebih maju, aku rasa sangat bangga melihat usaha mencuba jalan lain dilakukan untuk menaikkan taraf ekonomi kita. Kita terpaksa memungut ilmu daripada orang lain dan harus memberi ruang untuk pelajaran kita itu benar-benar dapat kita guna pakai untuk menolong diri sendiri. Kita bukannya menanam benih tauge yang boleh dituai dalam sehari dua. Kita sedang menanam benih jati yang akan menjadi sangat mahal selepas puluhan tahun. Kita harus bersabar kerana sabar itu bukannya separuh daripada Sabarudin… sabar itu separuh daripada iman.”
Nana berpaling ke arah Farid. “Sebagai anak, yang muda kena belajar menjaga bahasa. Jangan guna bahasa longkang apabila ingin didengar oleh orang yang lebih tua. Apa yang ingin kita ajarkan kepada generasi akan datang? Bagaimana mereka dapat belajar jika bahasa kita kasar, komen kita menyakitkan hati? Apabila bersuara, kita enggan mendengar suara orang lain. Kita duduk di kedai kopi dengan suara gagah berapi-api tapi kita setakat duduk di situ dan tidak akan ke mana-mana ataupun mendapat apa-apa melainkan dosa. Silap hari bulan, dapat ilmu hitam. Tiga hari, hati hancur. Jantung hancur. Anak bini merana.”
Nana menjeling Nina. “Yang tua pula, janganlah asyik nampak salah orang sahaja. Tegurlah secara baik. Kita ini emak dan bapa, jadi tugas kita mendidik. Jangan apabila anak melatah, kita pula bertempik, mengagah. Anak itu cerminan didikan kita. Apabila mereka buat salah, mungkin sebahagian daripadanya adalah salah kita. Pemimpin itu dipuji. Bukan dipuja. Bila menunjuk, jari tu jangan dulu arahkan kepada muka orang lain. Cuba arahkan ke muka sendiri, nasihat Nana dengan panjang lebarnya.
Nina dan Farid terdiam, saling bertukar pandangan, memikirkan perkara yang sama. Malu mendengar teguran Nana. Akhirnya Farid meminta diri untuk pulang. Sebelum melangkah, dia sempat bersalam dan meminta maaf.
Selepas Farid pergi, Nina merenung seketika tentang sikap mereka yang kebudak-budakan. Hanya kerana perbezaan pendapat, mereka sanggup bertegang urat dan bertengkar. Masalah mereka itu masalah kecil dan bukan pun hanya masalah mereka berdua. Namun dalam hatinya Nina berjanji, pada masa hadapan dia akan lebih berhati-hati dalam mengungkapkan kata, bimbang akan menggores perasaan orang lain. Apa lagi perasaan anak buahnya sendiri.
“Sikap aku tidak wajar.” Nina mengakui.
“Itulah pasal! Tali persaudaraan ibarat air, ia tidak akan luka, calar mahupun putus jika dicencang,” balas Nana.
“Aku akan membawa pendapat Farid itu ke pengetahuan Haji Rahman,” Nina berjanji.
“Baguslah. Dapat juga menjernihkan keadaan,” balas Nana. Dia sempat berfikir tindakan susulan Nina itu nanti akan dapat menyemat kembali anyaman persaudaraan yang telah longgar angkara perkara remeh-temeh yang hanya berbentuk jurang pendapat.
Glosari
aki datuk
unsu bongsu (panggilan)