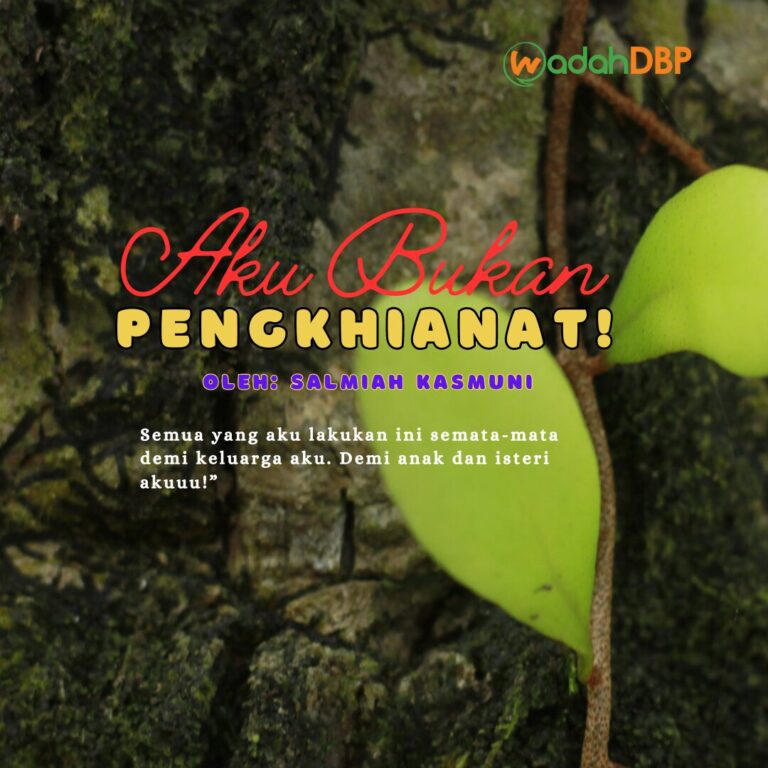1946 Penggaram
Biji-biji sempoa berlaga-laga apabila ditunjal oleh jari-jari yang dempak, berkuku hitam dan kotor.
“Mana boleh Mattt… hutang lama belum bayar maaa,” rengus Seng Kang apabila Kemat minta agar jumlah bayaran barang-barang keperluan dapurnya itu dicatat ke dalam buku.
“Sekali ni jeee.. Seng. Nanti aku dah ada duit aku bayarlah semua hutang-hutang aku tuuu,” pujuk Kemat. Dia tersengih, terpaksa.
“Lu latang sini naik apa?” soal Seng Kang seraya mengubah pokok perbualan. Kemat menghela nafas dengan matanya menghunjam ke halaman wajah apek tua di hadapannya.
Suasana khali seketika.
“Aku tumpang sampan Kamisan. Kebetulan dia mahu ziarah pamannya yang tidak sihat, yang tinggal berhampiran dengan dermaga.” Kemat sedikit merengus!
“Ohhh… Kamisan. Dia ada sampan ke?” soal apek tua itu lagi.
“Tentulah ada. Dulu aku pun ada sampan, tapi aku sudah tukar dengan beras,” jawab Kemat perlahan sambil mengucek-ngucek matanya.
“Hei, Seng! Jangan banyak tanyalah. Sekarang boleh aku ambil barang-barang?” soal Kemat agak keras. Dia bosan berlama-lama lagi berada di dalam kedai runcit yang pengap dan berbau asap colok Cina itu.
“Bolehhh, tapi kasi bayar. Lu punya hutang sulah manyak maaa!” seloroh Seng Kang lalu meninggalkan Kemat sendirian terkebil-kebil.
Kemat tenggelam punca.
Kemat mengaru-garu pelipisnya yang serabut berjambang sehingga menutupi sebahagian pipi cengkungnya. Wajahnya sedikit berkerut.
“Apa kerjanya tu, Seng?” soal Kemat setelah berkira-kira perlu atau tidak menerima tawaran kerja yang baru ditawarkan oleh Seng Kang.
Seng Kang tersenyum lebar. Dia menghampiri Kemat. “Itu macamlah kawannn!” Apek tua itu tertawa besar lalu menepuk-nepuk bahu Kemat.
“Itu sinang punye keleja,” Apek tua itu mencebek. Suaranya perlahan tetapi reaksinya agak angkuh. Kemat termangu-mangu melihat gelagat apek tua yang hampir sebaya dengan bapanya. Namun, bapanya hilang tanpa dapat dikesan. Ada yang mengatakan, bapa Kemat telah ditangkap komunis dan dibunuh kerana menjadi mata-mata kepada tentera Jepun. Tidak ada sesiapa yang mengetahui di mana mayat ayahnya ditanam. Mungkin mayatnya telah dihumban ke dalam lubang bersama-sama mayat-mayat yang lain. Lalu, lubang itu ditimbus dan disimen render di atasnya.
“Lu tolong bawa ini balang masuk hutan,” kata Seng Kang kepada Kemat sambil tersenyum sinis. Suaranya separuh berbisik dan wajahnya terlihat tenang dalam mengatur kata. Apek tua itu memandang Kemat dengan ekor matanya dan dapat menghidu keresahan Kemat yang berdiri tercegat di hadapannya.
“Masuk hutan? Lu gila ka? Masuk hutan itu bererti aku mahu jumpa komunis.” Kemat terjerit kecil sambil matanya tersembul memandang apek tua yang tersengih-sengih, mengejek.
“Lu jangan sombong maaa… ini pun keleja juga. Anak bini lu perlu kasi makan. Lu juga mahu makan, kalau tak keleja, lu satu keluarga apa mau makan?” Seng Kang sedikit merengus. Dia mengerling ke arah Kemat sehingga matanya terperesuk seperti terpejam.
“Kalau lu setuju bawa ini balang masuk hutan, lu boleh ambil beras, gula, garam dari ini kedai,” tambah Seng Kang lagi dengan suara perlahan lalu meninggalkan Kemat tercegat dengan mata terkebil-kebil. Apek tua itu tahu, Kemat tentu setuju akan tawarannya itu. Biasanya, orang dalam kesusahan, apa-apa sahaja yang disuruh pasti akan dilakukan. Itulah fikiran Seng Kang, apek tua yang sudah lama mengenali Kemat dan orang-orang Melayu di kampung Penggaram.
‘Rupa-rupanya dia adalah salah seorang daripada anggota Bintang Tiga. Nampak bodoh-bodoh, tapi pintar berpura-pura,’ detik hati Kemat. Ada sedikit marah pada apek tua yang sudah lama berdagang di kampungnya.
Kemat terkedu. Dadanya berdebar agak kencang. Gelisah.
“Baiklah, Seng. Aku setuju untuk bawa barang yang kau katakan tu ke dalam hutan,” jantung Kemat berdegup kencang. Dia tidak tahu mengapa perlu bersetuju dengan pekerjaan yang ditawarkan. Sedangkan pekerjaan yang ditawarkan itu adalah satu pengkhianatan kepada bangsa dan bentala leluhur tempat kelahirannya.
“Itu macamlah kawannn…,” Seng Kang ketawa besar. Dia telah menduga, Kemat akan setuju dengan tawarannya. Dia tahu, Kemat tidak punya semangat juang seperti lelaki-lelaki Melayu lain di kampung itu. Kalau ada sekali pun, dia terpaksa membelakangi demi mulut anak isterinya yang perlu disuap setiap hari. Seng Kang tahu benar, Kemat boleh diculik hatinya hanya kerana bimbang anak isterinya akan kebuluran.
“Lu masuk hutan bila matahali sudah hilang. Lu jangan kasi tau orang kampung walaupun lu punya bini sekalipun!” terang Seng Kang dengan suara perlahan. Matanya melilau memandang sekitar kedainya yang berbahang pengap itu.
“Mesti ingat, jangan buka mulut pada orang kampung. Kalau lu buka mulut, lu mati,” pesan Seng Kang apek tua itu. Pesannya ada ugutan yang memperingatkan Kemat kalau berkhianat! Kemat hanya mengangguk-angguk dengan keluhan kecil terpacul dari kerongkongnya.
“Ini balang bawa sekali balik lu punya lumah. Tapi… jangan kasi olang nampak.” Seng Kang menunjukkan sebuah guni yang agak besar tersandar di sebelah dinding. Kemat memandang lesu ke arah guni tersebut tanpa tahu isi di dalamnya.
“Lu masuk hutan, nanti lu lalu hujung kampung. Ada satu lolong dekat dengan kebun getah Haji Seman,” kata Seng Kang lagi. Suaranya perlahan seperti berbisik. Kemat mendekatkan telinganya pada mulut Seng Kang.
“Haji Seman sutak lama tidak memotong maaa. Takut sama Jepun!” Seng Kang tersenyum. Hatinya berasa puas kerana dapat memujuk Kemat agar menjadi tali barut komunis yang dikenali sebagai Bintang Tiga. Baginya, tidak semua pemuda Melayu di kampung itu berjiwa waja untuk mempertahankan bentala leluhur mereka. Orang-orang seperti Kemat inilah yang sentiasa diintai oleh Bintang Tiga untuk dilamar sebagai tali barut mereka. Malah, orang seperti Kemat mudah diperkuda demi cita-cita mereka untuk menawan negara ini ke dalam genggaman mereka. Kerana kesusahan hidup, ada dalam kalangan orang Melayu yang sanggup menggadai maruah bangsa dengan menjadi tali barut komunis. Buktinya ialah Kemat. Seorang pemuda Melayu yang berjiwa layu, sanggup melakukan apa-apa sahaja demi menjaga perut anak dan isterinya.
“Haji Seman bukan takut Jepun, tapi tak mahu dirinya dipergunakan oleh Bintang Tiga. Bintang Tiga suka peras ugut, mengancam, membunuh dan membakar rumah orang-orang kampung yang tak mahu menjadi sebahagian daripadanya.” Seperti ada kuasa yang menggerakkan lidah Kemat agar dia bertutur begitu. Namun begitu, perbuatan Kemat tidak sealiran dengan pemikirannya. Kemat tidak mahu Jenab dan dua orang anaknya jauh dari menjamah nasi, dia sanggup menerima tugas itu walaupun akan dilabel sebagai pengkhianat bangsa dan negara.
“Kalau masuk hutan, lu cakap itu macam… lu tak boleh balik jumpa anak bini lu lagi, maaa. Lu mesti mati punya!” Wajah Seng Kang sedikit berkerut.
“Kalau aku masuk hutan, aku mahu jumpa siapa?” soal Kemat.
“Nanti ada olang tunggu lu depan markas. Lu bagi ini balang pada olang yang tunggu di luar markas,” terang Seng Kang sambil berbisik.
“Lu cakap, tikus hutan, tikus hutan, tikus hutan. Cakap itu macam sebanyak tiga kali,” bisiknya lagi. Takut didengari oleh orang kampung yang mungkin mendengar perbualannya dengan Kemat.
“Itu kita punya kod.” Sedikit terbeliak mata apek tua itu memandang Kemat.
Kemat mengangguk-angguk tanda setuju. Dia ingat setiap pesanan Seng Kang. Dia terbatuk-batuk kecil. Kerongkongnya tersumbat asap colok Cina yang dibakar tidak jauh dari tempat dia berdiri.
‘Menjaga maruah bangsa itu pasti. Tetapi, dalam masa yang sama, anak-anak bangsa kekurangan makanan. Adakah bangsa boleh diwarisi sedangkan ramai anak-anak yang kebuluran dan mati?’ Kemat menggenggam kedua belah tangannya.
‘Aku bukan pengkhianat… sekadar mencari makan buat anak isteri ku,’ rintihnya dalam hati.
Dia melangkah lesu dari kedai Seng Kang dengan membawa sekarung barang-barang dapur dan sebuah guni yang agak besar. Di dalam kantung itu ada beras, garam, tepung, gula dan entah apa-apa lagi yang disumbat oleh Seng Kang. Manakala guni yang besar itu, tidak diketahui akan isi di dalamnya. Kemat teringat pesanan Seng Kang agar jangan sekali-kali membuka guni itu.
‘Ahhh… peduli apa kalau apek tua tu tak nak bagi tau, tak penting pun!’ detik hati Kemat. Yang penting bagi Kemat, untuk hari-hari berikutnya, Jenab dan anak-anak tidak perlu lagi memamah ubi rebus cicah ikan haruan bakar lagi. Mereka akan menghidu aroma nasi yang baru ditanak. lebih enak dan menyelerakan daripada ubi rebus.
‘Jenab tentu suka apabila dapat menjamah nasi,’ detik hati Kemat sambil tersenyum sendirian.
‘Pungel… kali ini kau akan makan nasi… bukan ubi, bukan keladi dan bukan keledek,’ bisik Kemat. Dia bermonolog, sambil tersenyum sendiri.
Sepanjang perjalanan menuju ke tepi sungai dia seolah-olah sedang berbual-bual dengan anak dan isterinya. Bibirnya menguntum senyuman. Kantung dan guni yang sarat di atas bahunya tidak dirasakan berat. Biar tiga kali ganda berat daripada itu pun dia mampu memikulnya, asalkan perut anak dan isterinya terisi. Sekadar berat bahan-bahan yang boleh dijadikan habuan tekak dan mengenyangkan perut anak isterinya, apalah sangat bagi Kemat. Dia tersenyum lagi.
Sudah lama Kemat empat beranak mengisi perutnya dengan ubi rebus dan ikan haruan bakar. Kadangkala, menu ditukar kepada keladi rebus dengan belut paya pais. Belut pais biasanya dilumur dengan kunyit dan sedikit garam lalu dibakar di atas bara. Setakat ikan haruan dan ikan betik banyak terdapat di parit di belakang rumah Kemat. Manakala belut boleh didapati dari paya nipah, berdekatan dengan belukar tidak jauh dari rumahnya.
Jenab pula seorang isteri yang rajin bercucuk tanam. Di sekitar rumahnya ada beberapa batas ubi, keladi dan keledek yang boleh menampung perut mereka dari kebuluran. Namun, mereka tetap rindukan bau harum nasi yang ditanak. Mereka rindukan nikmat meratah nasi waima hanya berlauk ikan haruan bakar atau belut pais. Bagi Kemat nasi tetap nasi bukan ubi, bukan keladi atau pun keledek rebus.
Dia terus memasang angan-angan. Mahu membahagiakan keluarganya dengan makanan yang enak. Kemat juga berangan-angan mahu memberi persalinan baharu buat Jenab dan anak-anaknya. Tentu Seng Kang memberinya upah kerana menjadi orang perantaraan ke dalam hutan selain memberinya barang keperluan dapur. Sewaktu dia bekerja dengan Jepun memunggah beras dan garam di dermaga, hidupnya terbela. Setelah Jepun menyerah kalah, dermaga menjadi sunyi dan sekali gus Kemat hilang pekerjaan. Kemat lupa, semua orang kampung juga seperti keluarganya. Kekurangan bahan makanan dan juga tidak pernah bersalin dengan pakaian baharu. Negara sedang diuji dengan pelbagai ancaman. Sekiranya tidak daya membela negara daripada dijajah atau diancam anasir, memadai dengan menjadi seorang rakyat yang tidak mudah menjadi tunggangan si pengkhianat negara.
“Kau akan terkenal sebagai pengkhianat!!!”
“Hidup kau akan dilaknat oleh bangsamu sendiri!”
“Kau pengkhianat!!! Pengkhianat!!!”
“Kau memberi makan anak isterimu daripada sumber yang haram!!!”
Langkah Kemat terhenti. Dia menoleh ke kanan, ke kiri dan ke belakang. Gugup. Dia mencari arah datangnya suara itu. Tidak ada sesiapa di sekelilingnya, hanya semak-samun berwarna keemasan dek sorotan mega yang semakin menyuruti ke barat.
“Siapa tu?”
“Siapa???”
“Keluarrr! Tunjukkan diri kau!!!” Kemat menanti dengan debar sekiranya ada sesiapa yang keluar dari semak-samun itu. Hatinya melonjak rakus ingin melihat siapakah yang berani mengata dirinya seorang pengkhianat bangsa.
“Kau mana tahu! Semua yang aku lakukan ini semata-mata demi keluarga aku. Demi anak dan isteri akuuu!”
“Sekadar setuju membawakan barang ke dalam hutan, bukan pengkhianat namanya … bukannn!”
“Perut anak isteri aku perlu diisi dengan nasiii. Kau tahu?” Kemat terlolong-lolong bagai disampuk jembalang senja. Suaranya bergema, bersahut-sahutan sehingga ditelan rimbunan semak-samun lalu hilang begitu sahaja. Khali… sepi kembali. Hanya keriuhan kicak-kicau burung-burung perling yang berebut dahan untuk beradu.
Kemat mempercepat langkahnya menuju ke pelantar di tepi sungai.
“Pengkhianat!!!”
“Pengkhianat bangsa!!!”
“Pengkhianat tanah air!!!”
“Tidakkk! Kau yang pengecut! Kau tidak berani menghadapi kenyataan. Kenyataan yang keluarga kau juga akan kebuluran. Anak isteri kau tidak makan… anak isteri kau akan mati kebulurannn!” Langkah Kemat semakin laju. Dia mahu cepat sampai ke pelantar di tepi sungai. Dia tidak mahu melayan suara yang penakut itu. Hanya orang-orang yang penakut sahaja memberi amaran dengan bersembunyi.
“Wahhh, banyak kau berbelanja Mat!” Ternganga mulut Kamisan memandang Kemat yang tercungap-cungap meluru ke buritan sampan dan menghempaskan guni dan kantung yang dipikulnya. Kamisan kehairanan.
“Barang-barang dapur ni, San. Dah lama anak bini aku tak jamah nasi. Hari-hari makan ubi dan keladi rebus saja,” seloroh Kemat dengan suara gementar. Dia membuka kain lilit di kepalanya lalu menyeka peluh di dahi. Kamisan masih dibelenggu kehairanan.
‘Tak kan barang dapur banyak macam tu?’ berbagai soalan terbit dalam hati Kamisan. Dia berasa sedikit curiga dengan sahabatnya.
“Ha… paman kau macam mana? Dah sembuh?” soal Kemat selamba.
“Dah kebahhh … tadi masa aku nak balik, dia dah boleh bangun sendiri,” jawab Kamisan. Dia duduk menjaga kemudi dengan pendayung.
“Kalau pantas mendayung, sebelum habis maghrib sampailah kita,” ujar Kamisan. Rokok daun di penjuru bibirnya sudah tidak berbara. Sengaja dibiarkan terjuntai buat bahan gigitan untuk menghilangkan gatal di gusi. Matahari semakin condong ke barat. Sungai, airnya tidak mengalir deras seperti selalu. Mungkin air laut belum naik pasang.
“Kalau kau penat, biarlah aku yang mendayunggg,” pelawa Kemat.
“Tak mengapalah, aku dah biasa mendayung sewaktu air cetek,” seloroh Kamisan. Suasana sepi semula. Kocakan air dari tolakan pendayung kayu seakan-akan lesu pergerakannya. Kemat kelihatan agak gelisah. Sekejap-sekejap punggungnya dialihkan ke kiri, kadang berubah pula ke kanan.
“Ada bersisa satu lagi ni, Mat. Rezeki engkau ni,” Kamisan menghulur sepuntung rokok daun kepada Kemat.
“Eih, boleh juga,” balas Kemat lalu mengepit pangkal rokok daun ke bibirnya. Kamisan menghulur api mancis belerang ke rokok daun yang terkepit di bibir Kemat.
Kemat menyedut dalam-dalam rokok daun yang telah berbara.
“Sedap, berangin. Tembakau apa ni, San?” tanya Kemat sambil menghembus kepulan asap dari celah bibirnya.
“Tembakau tu biasa aje, Mat. Aku cuma tambahkan cengkih aje,” balas Kamisan sambil tersenyum.
“Cengkih tu aku beli sewaktu ke Singapura sebelum kedatangan Jepun,” kata Kamisan lagi.
“Lama tuuu,” kata Kemat dengan mengangguk-angguk. Sampan meluncur perlahan kerana melawan arus air ke muara. Pendayung kayu juga lesu namun, teriakan cengkerik bagai menghidupkan suasana senja yang menggamit malam. Sesekali mata Kamisan tajam menghunjam sebuah guni yang tertonggok di buritan sampan.
***
Sinaran lembut cahaya bulan bagai membelai bumbung-bumbung rumbia di kampung Parit Ketapang. Bintang-bintang pula bagai manik yang bertabur luas di angkasa. Sang Pungguk turut melahirkan rasa kecintaannya terhadap bulan dengan lontaran gumam suaranya. Pendek kata, suasana pada malam itu seindah susunan ilham bagi coretan orang-orang seni. Namun, seorang isteri hanya ditemani dengan cahaya suram dari sumbu pelita sedang sarat gelisah menunggu suaminya pulang.
Bunyi kuakkan pintu berkeriut. Derap tapak kaki menginjak lantai, lembut dan perlahan. Dingin angin malam mengekori, menjamah sumbu pelita lalu cahayanya meliuk-liuk.
“Kau dari mana? Kokok ayam sudah tiga kali riuhnya,” Jenab tertonggok di birai pangkin kayu dengan matanya tajam menghunjam wajah suaminya. Kemat sedikit tersentak.
“Dari rumah Sekak. Kau tak tidur lagi?” jawab Kemat acuh tak acuh sambil membuka lilit di kepalanya. Juga, membuka pakaiannya yang sepelat dengan tanah dan berbau hapak. Dia menarik pelekat yang tergantung di tepi dinding lalu menyarungnya dengan melipat dan menggulungnya ke pinggang. Badannya berlengeng tanpa berbaju.
Jenab melengos dengan keluhan.
Dari samar-samar kerdipan cahaya pelita, Kemat mencuri lihat ke wajah Jenab isteri kesayangannya. Dia pulang lewat malam begitu, bukan bererti cinta dan sayangnya terhadap Jenab telah lupus. Tetapi, ada sesuatu yang memaksa dia berbuat begitu tanpa boleh diberitahu kepada Jenab.
“Mahu ziarah orang, siang sajalah, kang! Malam begini bahaya. Kau bukan tak tahu, sekarang ni musim Bintang Tiga mengganas,” sedikit merengus, Jenab memandang Kemat.
Kemat tidak menjawab. Sebaliknya dia terus berbaring bersebelahan dengan kedua orang anaknya. Pungel, anak lelaki sulung berusia lima tahun, manakala Aton anak perempuan mereka baru berusia dua tahun. Jenab menggeleng-geleng lagi apabila dilihat suaminya telah pun melarik irama dengkur.
“Nampak sangat letihnya… buat apa agaknya ke rumah Sekak tuuu?” rungut Jenab lagi. Sebagai seorang isteri, Jenab berasa sangat khuatir apabila suaminya pulang lewat, lebih-lebih lagi pada waktu malam. Bintang Tiga akan menangkap siapa sahaja yang dilihat merayau-rayau pada waktu malam. Semenjak Jepun menyerah kalah, Penggaram dan kampung-kampung sekitarnya sentiasa diintai oleh Bintang Tiga.
Jenab teringat kata-kata Wak Salekah tentang Kemat di kedai Wak Karim beberapa hari yang lalu.
“Engkau kena awasi dan tengok-tengokkan Si Kemat tu,Jenab… aku ada dengar orang-orang kampung cakap, Kemat tu menjadi tali barut komunis.” Kata-kata Wak Salekah bagaikan hujung gunting yang menerobos gegendang telinga Jenab.
“Kalau ya pun jadi tali barut komunis, tentu aku tahu, Wak,” jawab Jenab dengan lontaran senyuman yang terpaksa. Walaupun dalam hatinya juga turut meragui akan gerak-geri suaminya. Semenjak Jepun tidak lagi mengehendaki perkhidmatan Kemat di dermaga kecil untuk memunggah beras dan garam ke darat, Kemat selalu keluar rumah sehingga lewat malam.
‘Mungkin sedang mencari pekerjaan,’ bisik hati Jenab. Setidak-tidaknya dapat menepis cuak di hatinya sendiri. Jepun menutup dermaga kecil itu semenjak serangan Bom Atom Amerika Syarikat ke atas Hirosima dan Nagasaki di Jepun. Jepun telah menyerah kalah sekali gus tidak lagi menawan Tanah Melayu dan berakhirnya Perang Dunia Kedua.
Kemat tidak ada lagi punca pendapatan untuk membeli beras hancur sekali pun.
Tapak rumah sekangkang kera itu tidak ada hasil selain daripada tanaman kontan. Itu pun hasil usaha Jenab yang rajin berbudi kepada tanah. Ubi, keladi dan keledek itulah yang dapat menyambung nafas mereka empat beranak. Jenab memang seorang isteri yang rajin dan penyabar. Kemat tahu itu. Dek kerana itu, Kemat tidak pernah mengambil hati setiap teguran Jenab. Dia tahu, tingkah lakunya semenjak tidak lagi bekerja dengan Jepun, tidak disenangi oleh Jenab.
“Kemat! Kemat!” Ada suara keras memanggil dituruti dengan ketukan pintu bertalu-talu. Tanpa berfikir jauh, Jenab bingkas bangun dan membuka pintu.
“Kemat mana? Kemat! Kemat!” Beberapa orang yang menutup mukanya meluru ke dalam rumah. Kemat digugah. Tanpa berbasa-basi, Kemat diheret keluar rumah. Jenab ditolak dengan kasar oleh salah seorang yang bertutup muka agar jangan mencampuri urusan mereka.
“Jangan keluar, kalau nak selamat,” ugut orang yang bertutup muka itu.
“Kang… kenapa ni? Kenapa?” soal Jenab. Tanpa mengindahkan ugutan, Jenab berlari mendapatkan Kemat. Namun, langkah Jenab sumbang. Dia terjelepok di atas tanah. Kakinya tergeliat dan tidak mampu untuk berdiri. Dari jauh Jenab hanya mendengar orang-orang yang menutup mukanya seperti sedang mengherdik Kemat.
“Kau tahu? Seng Kang telah dibunuh oleh pengikut-pengikut Kiyai Salleh. Siapa yang membocorkan rahsia, kalau bukan kau?!” diikuti seperti bunyi tumbukan.
“Dia memang patut mati! Dia pengkhianat negara!” laung Kemat dengan terketar.
“Engkau memang tak tahu diuntung! Waktu kau susah, Seng Kang yang menolong keluarga kau dari kebuluran. Balasan yang kau beri, dengan membocorkan rahsia dia terlibat dengan perjuangan kami kepada gerakan pemuda Melayu?!!” Diikuti seperti bunyi tumbukan lagi.
“Siapa saja yang mengkhianati bangsa dan bentala leluhur ini, dia adalah urusan akuuu!” Dalam menahan kesakitan, Kemat tetap bersemangat.
“Allahhh!!!”
“Mampus kau! Mampus! Tak reti mengenang budi!!”
Suasana sepi. Jenab menguatkan semangat dengan berdengkot-dengkot mencari Kemat. Dari remang-remang cahaya bulan, dia melihat sekujur tubuh hanya dengan berkain pelekat, terbaring.
“Kang Kemat… mengucap kang. Mengucappp…,” Jenab tidak mampu berbuat lebih dari itu. Dia bingung. Dengan suara terketar, menahan kesakitan dan kepayahan, Kemat menceritakan mengapa dia terlibat dengan Bintang Tiga.
“Maafkan aku, Jenab. Selama ni… aku ke hutan membawa keperluan Bintang Tiga atas suruhan Seng Kang. Aku diupah dengan barang-barang keperluan harian kita. Semua tu demi kau, Pungel dan Aton… agar dapat meneruskan kehidupan. Namun, aku tidak mahu terus-terusan dilabel sebagai pengkhianat bangsa dan negara. Setiap pergerakan tali barut Bintang Tiga, telah aku maklumkan kepada Pergerakan Pemuda Melayu, anak buah Kiai Salleh…”
“Aku tidak mahu mati sebagai seorang pengkhianat bangsa dan negara… .”
Ada titis air jernih meluncur laju dari kolam matanya. Dengan nafas yang payah… Kemat teresak-esak.
“Sudahlah tu, Kang. Jangan banyak cakap. Mengucap Kang, mengucap…” Jenab tersedu-sedu sambil mengusap-usap perlahan dada suaminya.
“Selain Seng Kang, beberapa orang lagi di Penggaram yang terlibat dalam perjuangan Bintang Tiga… telah dibunuh oleh Pergerakan Pemuda Melayu…” Kemat memandang Jenab tidak berkelip. Nafasnya tersekat-sekat. Tubuhnya longlai di ribaan Jenab.
Jenab meraung…