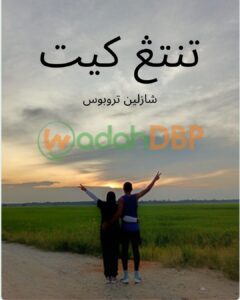SEPAHIT-PAHIT air kopi yang sedang dihirup, pahit lagi menelan kata-kata yang dilemparkan oleh ayah sebentar tadi. Sepanas-panas air dalam cangkir yang disentuh, lebih panas rasa hati yang tersentuh oleh hinaan ayah.
Perit untuk aku menahan kepedihan air mata yang tidak berhenti bergenang di kelopak mataku. Pedih yang dirasakan jiwa ini membuatkan aku gagal untuk melihat keindahan suasana sekeliling seperti selalu. Terlanjur aku dalam kelukaan ini, kusedari hakiki yang kejam berkali-kali menampar rona pucat wajahku.
Pagi tadi, kepulanganku ke rumah telah disambut oleh ayah dengan satu libasan tali pinggang di belakang tubuhku. Jatuh terduduk aku di atas kerusi rotan ruang tamu rumahku.
Seluruh kulit belakang tubuhku terasa merengsa bagaikan disengat jutaan kala jengking, bermula dari sudut bawah bahu kanan ke sudut kiri pinggang. Suaraku yang mengerang kesakitan umpama kalis dari jiwa simpati ayah. Dia terus menarik lengan kiriku dan memaksa aku berdiri semula. Dalam keperitan yang masih mampu ditanggung diri ini, aku berdiri di hadapan ayah dengan penuh persoalan.
Sebelum sempat lidah melafaz soal, tapak tangan kasar ayah sudah menampar pipi kananku. Kelonglaian badan yang disebat sebentar tadi menyebabkan kepalaku tidak mampu menahan kekuatan tamparan ayah dan terteleng ke kiri bahu. Berpinar-pinar pandanganku buat seketika sebelum aku sedar tubuhku sudah di atas kusyen kerusi rotan selepas ditolak oleh ayah dengan rakus.
Aku mengerang lagi. Sakit! Pedih! Perit! Sukar untuk aku gambarkan azab yang ditanggung pada saat itu. Namun, lebih sengsara apabila segala persoalan yang menerjah minda masih belum dijawab oleh ayah.
Ayah merengus berat dan melempar tali pinggang yang digenggam erat tadi ke lantai ruang tamu rumah yang lengang. Aku cuba membaca wajah bengis ayah apabila dia melabuhkan punggung ke kusyen kerusi rotan yang berada di hadapanku.
Mata ayah kutatap sambil menahan sakit. Entah mengapa mata berapi yang penuh amarah tadi, tiba-tiba berubah sayu dan bergenang air mata. Tapak tangan kanan ayah menumbuk telapak tangan kirinya berkali-kali sambil dia menggeleng-gelengkan kepalanya.
“Anak tidak mengenang jasa! Sejak kamu lahir, sudah membawa malang sehingga menyebabkan ibumu terkorban. Sekarang, kamu bawa bala dengan menconteng arang ke mukaku. Mengapa tidak kamu yang menggantikan tempat ibumu dahulu, mengapa?” bebel ayah dengan air mata yang sudah mula mengalir dari kelopak matanya.
Ayah mula membuka lipatan peristiwa yang menghiris hatinya. Sejak aku dibebaskan daripada pusat pemulihan sebulan yang lalu, hidup ayah tidak pernah tenang. Dia sering mendapat tohmahan daripada jiran tetangga tentangku.
Kain di ampaian yang hilang ditiup angin, dikatakan aku yang mencurinya. Basikal dan motosikal mula dirantai erat di tiang rumah masing-masing, khuatir kalau-kalau aku mencurinya. Malah, anak-anak gadis ke sekolah telah diingatkan agar membawa payung sebagai senjata sekiranya aku hendak menyerang mereka.
Prejudis yang berleluasa di tetangga ini ditelan ayah secara bisu. Dia menerima takdir bahawa anak tunggalnya ini mengecewakannya kerana pernah menjadi ikan bilis suruhan di pusat pengedaran dadah yang dijuarai oleh jerung bengis bertopengkan insan biasa.
Cuma pagi tadi usai dia bersolat subuh di surau , dia ditusuk berita umpama duri berbisa yang menghancurleburkan segunung doa pengharapan agar aku mendapat peluang kedua menjadi insan yang soleh dan diterima oleh masyarakat.
“Kamu tak tahu ke, Ali? Anak dara si Hasan tu dah dirosakkan oleh anak kamu. Malam tadi, nasib baik sempat dijumpai oleh Hasan dalam tandas. Dah potong urat nadi di tangan. Nasib tak arwah budak tu. Macam mana kamu jaga anak, Ali? Dah letih main ketum, main anak dara orang pulak?”
Ayah terlalu percaya bisikan jiran-jiran tentang aku. Ayah terlalu melayan kebisingan guruh di langit sehingga lupa ketenangan tasik di darat. Ayah terlalu memandang hempasan ombak tanpa memandang pasir yang kesakitan.
Aku masih terduduk menahan kesakitan di ruang tamu rumah. Tangis kecewa ayah turut mengoyak jiwaku. Mahu saja aku pergi memeluk ayah dan menenangkannya, tetapi entah bagaimana mahu aku ceritakan kebenarannya. Mampukah aku warnai pelangi pada langit kelabu pekat yang mengaburi ayah?
Tanpa bicara, aku berlari ke luar rumah tanpa sebarang lafaz dan meninggalkan ayah sendirian. Di gerai Mak Jah, aku menghirup secangkir kopi dengan linangan air mata.
Aku tidak menafikan bahawa aku ada menemui Hazel, anak Pak Hasan petang kelmarin. Aku juga tidak menafikan bahawa aku mempunyai perasaan terhadap gadis berkulit putih kuning itu sejak di bangku sekolah lagi. Sumpah, aku tidak pernah sekali pun beralih rasa kepada gadis lain selepas mengenalinya.
Hazel juga mempunyai perasaan yang sama terhadapku. Dia tidak pernah berpaling daripada janji-janji yang termeterai antara kami, walaupun aku menghabiskan masa selama dua tahun di pusat pemulihan. Hal ini kerana, hanya dia sahaja yang tahu sebab sebenar aku terjebak ke kolam bernajis dadah.
“Biarlah Hazel yang beritahu ayah Asif perkara yang sebenarnya, ya. Hazel tak sanggup tengok Asif terus-menerus dipandang jijik oleh ayah. Lagipun, semua yang berlaku adalah kerana dia juga. Jika dia tidak berhutang ke sana ke mari disebabkan judi, mustahil untuk Asif terjun ke dalam kolam hina itu. Dia patut tahu, Asif!”
Kedegilanku untuk tidak membersihkan nama sendiri dan tidak memburukkan ayah ternyata lebih melukai perasaan Hazel. Dia tahu aku ditangkap oleh pihak berkuasa semasa sedang merebus air ketum di sebuah bangsal di tetangga jiran. Dia juga tahu bahawa aku didatangi oleh lintah darat yang menuntut hutang judi ayah sehingga menyebabkan aku pendek akal dan bersetuju dengan jerung ketum untuk menyertainya. Disebabkan aku baharu berusia 15 tahun dan tidak disabitkan kesalahan mengedar, maka pusat pemulihan menjadi ruang sempit buatku menerima hukuman dunia.
Namun aku lebih menyesali kedangkalanku ketika berhadapan dengan Hazel kelmarin. Dia mahu aku menyelamatkannya daripada akad keterpaksaan orang tuanya. Dia mahu aku menjadi pelafaz akad yang sah akan dirinya, bukan pemuda pilihan keluarganya. Dia mahu aku membersihkan namaku daripada kekotoran yang bukan milikku.
Sayang, aku menolak hasratnya itu. Aku tidak mahu memburukkan ayah. Aku tidak mahu menyapu debu ke wajah ayah. Biarlah aku mengorbankan hasrat menjadikan Hazel suri hatiku asalkan dia dan ayah mendapat kehidupan yang lebih baik dan mulia.
Tidak aku sangka bahawa Hazel sanggup mengelar nyawanya sendiri kerana kecewa dengan penolakan itu. Malah, lebih memburukkan keadaan apabila perbuatan Hazel disalah tafsir oleh tetanggaku dengan fitnah bahawa aku ialah si tupai yang menebuk maruah gadis polos itu. Sedangkan Hazel masih sunti kerana aku tidak pernah menyentuh tubuhnya walau sekelumit.
Secangkir kopi yang licin dihirup, aku tinggalkan di atas meja kayu di gerai Mak Jah selepas membayar harganya. Aku mengatur langkah longlai tanpa haluan. Minda masih berserabut dengan kata-kata hinaan ayah, tindakan kurang waras Hazel dan juga perilaku tetangga yang tidak akan pernah menerima kepulanganku.
Tubuh yang masih perit menerima libasan tali pinggang ayah terasa mencucuk-cucuk sehingga ke tulang. Tulang rahang kanan juga terasa membengkak selepas menerima tamparan amarah ayah. Langkah-langkah yang kususun di bawah panas suria tengah hari ini terasa berat dengan semua penyesalan yang tidak mungkin berbalas murni.
Di sebalik silau suria, aku terlihat kelibat si lintah darat yang pernah mendatangiku kerana hutang judi ayah sedang menjalankan urusan dengan pihak ketiga. Bagaikan ada bisikan halus di gegendang telinga yang menasihatiku untuk melaporkannya kepada pihak berkuasa. Lebih membara lagi apabila jiwaku pula memberontak dan memaksa aku untuk pergi melepaskan amarah dan penyesalan terhadapnya kerana dia adalah sebab utama aku menjadi ikan di dalam kolam bergelodak tragis.
“Ayah, maafkan Asif. Hazel, maafkan Asif. Doakan yang baik-baik buat Asif kerana Asif tidak mampu menjadi yang terbaik atau tersuci buat kalian. Tetanggaku, sebaiknya kalian cuba menggali kebenaran dan bukan semakin mengeruhkan gelodak yang sudah keruh. Kali ini aku akan pastikan tiada lagi mangsa lain yang akan berkesudahan seperti nasibku. Lintah darat ini harus kubenamkan ke dalam bukitan garam, biar dia lesap daripada terus menghisap darah-darah mereka yang dangkal.”
***
“Hazel”
Bisikan sayup yang singgah ke gegendang telinga Hazel menyedarkan dia daripada keadaan koma. Perlahan-lahan kelopak mata yang tertutup selama dua hari dibukanya. Terpandang wajah senyum syukur milik ayahnya, Pak Hasan dan ibunya, Mak Chah.
Selepas mengumpul kekuatan, Hazel tidak menunggu lama. Dia terus memohon untuk menemui ayah dan aku. Dia mahu memberitahu kebenaran kepada ayah. Dia juga mahu membersihkan namaku.
Pak Hasan sekadar menunduk lemah. Mak Chah juga mula kelihatan serba salah. Mereka tidak mampu berkata-kata. Pak Hasan menghulurkan surat khabar hari ini kepada Hazel tanpa sebarang lafaz.
Hazel yang kebingungan pantas memakukan bebola mata ke arah tajuk utama akhbar di tangannya. Bagai pecah seribu, jiwa gadis itu berkecai bersama-sama darah tidak berwarna yang mengalir daripada kelopak mata yang mengharap untuk tertutup abadi.
“BEKAS PELATIH PUSAT PEMULIHAN MANGSA BUNUH LINTAH DARAT.”