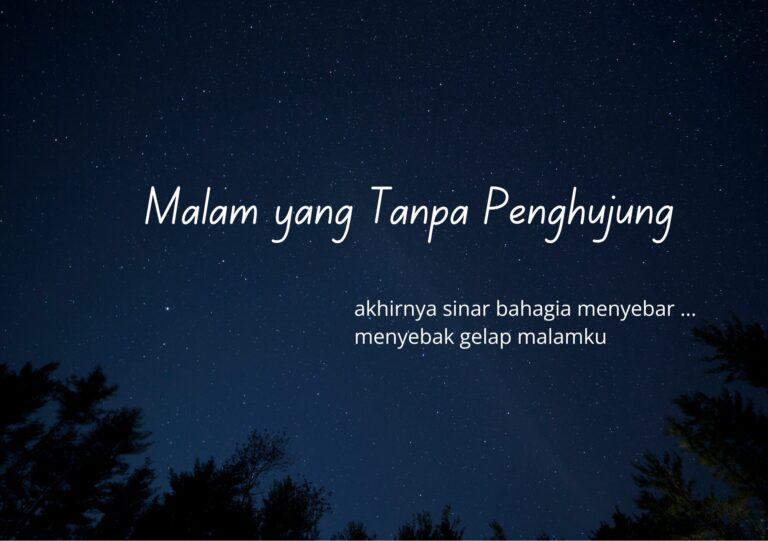SETIAP detik … pada malam mahupun siang, sebuah jiwa akan terlahir dalam lingkaran takdir derita mahupun bahagia.
Setiap detik … pada malam mahupun siang, mereka lahir bersama nukilan cereka tanpa pilihan. Ada jiwa yang hadir dalam jalur kebahagiaan yang sentiasa manis. Ada jiwa yang terlahir untuk melewati malam yang tanpa penghujung.
Malam itu bagai enggan berakhir menjadi siang, seperti senada dengan cerita hidupku. Entah mengapa aku terlalu sukar untuk melelapkan mata. Getar jantungku pantas tanpa irama, seperti seekor rama-rama yang terkurung dalam balang kaca. Pelbagai rasa teradun di situ.
Seram.
Seronok.
Takut.
Teruja.
Menunggu.
Tertunggu-tunggu.
‘Esok?’ bisik hatiku, masih menganyam keraguan.
‘Esok!’ Hatiku berbolak-balik, namun iramanya semakin pasti.
‘Ya … esok!’
Akhirnya aku memutuskan dengan tekad dan keberanian yang seperti buih, yang kian menjadi sebuah gelembung besar yang bakal pecah, terbang bersama angin masa.
Aku telah menghitung dan mengira semuanya. Aku telah memikirkan kesan dan akibatnya agar air yang kutampar nanti tidak akan memercik semula ke muka.
Aku tahu, aku tidak akan gagal. Aku tidak boleh gagal … kerana ini bukan percubaan pertama untuk bakal kesekian kalinya. Ini harus berhenti di sini. Hari ini. Ia harus untuk kali pertama dan terakhir. Aku memang punya pilihan … untuk terus atau undur. Namun aku pilih untuk mengakhiri semuanya.
Duri yang menikam daging ini sudah terlalu lama menimbulkan sakit dan nanah. Ia harus dicabut, dan apabila duri itu hilang, yang lainnya akan ikut terhakis. Semua nanah dan darah yang hanyir akan hilang. Dan akhirnya luka itu akan sembuh jua diubati masa. Aku tahu itu.
Duri yang menyeksa ini harus dihapuskan kerana aku sudah terlalu bosan menanggung.
Aku terlalu lelah. Malam yang panjang ini harus ada penghujungnya. Segalanya harus berakhir.
Harus!
***
Dia terangguk-angguk menikmati sarapan paginya. Menikmati setiap titis teh tarik panas yang dihirupnya.
“Kau guna apa ini?” soalnya, menjeling ke arahku yang berdiri di sudut kirinya, menunggu arahan yang seterusnya.
“Seperti biasa, bang…”
“Tapi kualiti masakan kau berlainan sejak akhir-akhir ini. Lebih sedap. Bukan seperti makanan beracun yang kau hidangkan sebelumnya …” ucapnya semacam satu pujian.
Aku menyeringai dalam hati. Hanya aku tahu kenapa. “Saya hanya hidangkan yang terbaik dan berkhasiat. Gulanya saya ganti dengan glukosa …”
Belum sempat kuhabiskan kata-kataku, dia tiba-tiba menjerit kesakitan, menyentuh dadanya. Mukanya pucat dan berpeluh-peluh.
“Abang tak apa-apa?” soalku, memandang wajahnya dengan penuh tanda tanya.
Lelaki itu tercungap-cungap. Wajahnya berkerut-kerut. Kepala digelengkan.
‘Hari itu … muntah! Kelmarin … muntah! Hendak muntah lagikah?’ hatiku berbisik namun kutekan sebarang riak yang melintas di wajahku. Kubiarkan jiwaku berbicara.
“Jangan pedulikan aku! Aku tak apa-apa!” katanya .
Tangan kanannya terangkat, mengawang sejenak, memberi isyarat agar aku tidak menghampirinya. Aku menegakkan tubuh. Menahan diri daripada bergerak mendekat untuk membantunya.
“Abang hendak saya panggil Mat? Kita pergi ke …”
Dia mengangkat wajah. Memandangku sekilas dengan pandangan seperti seekor singa yang terluka dan lapar. Entah bila tangannya bergerak, aku tidak sempat terlihat. Yang kusedar hanyalah bantingan objek keras, dentingan benda berat jatuh, dan bunyi kaca berderai sesaat selepas rasa sakit yang amat sangat. Aku tidak pun sempat mengelak ketika benda keras itu hinggap di wajahku.
“Sudah berapa kali aku cakap … aku tidak mahu pergi hospital!” teriaknya, kembali terbongkok dan tercungap-cungap.
Aku menekup muka, tidak sempat rasa sakit menapak di hatiku mendengarkan nada suaranya yang sangat tinggi … kerana kesakitan itu berkumpul di sekujur wajahku. Sakit yang teramat sangat.
Ada sesuatu yang hangat mengalir dari dahi … dan juga dari kedua-dua belah hidungku. Ketika kuangkat telapak tangan, darah merah segar bertitisan jatuh ke baju. Tompokan merah mulai merona di atas marmar rumah yang seputih gading.
“Abang …!” aku berbisik, ingin menagih perasaan simpatinya.
Namun dia menghadiahkan aku dengan jelingan benci dan cuak.
“Kau yang hendak sangat, kan …!” ucapnya dengan suara dingin.
Aku tahu itu. Aku memang sudah agak itulah reaksi yang bakal aku terima.
“Habis pecah bekas habuk rokok aku! Aku beli dengan harga yang mahal. Nanti kau ganti!”
Semua ini tentu salahku. Deritaku ini … kesakitanku ini tidak pernah layak untuk mendapat simpati. Kerana aku yang mengundang kemarahannya. Aku yang meminta kebenciannya. Semua ini tentu sekali salahku.
“Kau memang tahu aku paling tak suka pergi ke hospital. Selama ini aku belum pernah lagi dengar apa-apa perkara baik setiap kali aku ke hospital,” katanya.
Dia melotot, memandang sekujur diriku yang tidak punya apa-apa nilai di matanya. Dia berpaling, seolah-olah dengan memandangku telah menyakitkan matanya.
“Jaga kesihatan! Jaga pemakanan! Pantang itu! Pantang ini!” desisnya.
Aku tunduk, melihat bayangan wajahku terbias dari lantai marmar di bawah kakiku.
“Daripada aku berhenti makan itu, minum ini … lebih baik kau terus bubuh racun dalam makanan aku! Senang!” Suaranya menderam, keluar dari rasa yang amat geram.
Jantungku tersentak. Bergetar. Bergegar. Darah segar masih terus menitis ke lantai. Setitis mengenai bias bayangan mataku. Setitis lagi. Setitis lagi … sehingga aku rasa titis-titis itu meronai seluruh bayanganku yang terbias sedih di atas permukaan marmar.
“Kau pergi bersihkan diri kau! Lepas itu bersihkan lantai! Aku paling benci dengan sikap kau yang pengotor. Pergi!” usirnya tanpa sesaat pun memandangku. “Dan jangan lupa tentang bayaran sekolah anak-anak aku …” tambahnya sebelum aku memulakan langkah.
Aku mengangguk. Berlalu untuk menurut segala perintahnya. Ketika itu juga telefon bimbitnya berdering. Dia pantas menjawab. Hilang sudah kesakitan dan kemarahannya. Dia tersenyum paling manis. Bersuara paling lembut …
“Selamat pagi, Qish …” ucapnya tanpa segan silu, lantas berpaling membelakangiku.
Aku tahu siapa yang berada di hujung talian. Balqish. Teman baikku.
“Hendak pergi membeli-belah di mana hari ini, sayang?” soalnya separuh berbisik.
Terasa kegelapan malam kembali membungkusku. Seorang lagi manusia yang paling kupercaya ternyata menikamku dari belakang. Balqish, bekas teman baikku!
***
Aku melangkah memasuki ruang kamarku yang sempit, mencapai tuala lalu bergerak menuju ke arah tandas di bahagian belakang. Tandas yang kukongsi bersama Kiah, pembantuku.
Kiah kuambil bekerja bukan untuk meringankan kerjaku kerana semua kerja di rumah ini kulakukan sendiri. Atas perintah, kerana suamiku tidak mempercayai orang lain untuk menyediakan keperluan hariannya. Kerana aku ada. Kerana itu adalah tugasku.
Kiah kuambil bekerja dengan syarat dan peraturan yang keras dan ketat. Syarat utama buat Kiah adalah dia sama sekali tidak boleh masuk ke ruang dapur kecuali untuk menyediakan makan dan minum untuk dirinya sendiri sahaja.
Kiah merupakan sisa pembantuku yang mampu bertahan. Kerana dia memahamiku dan kasihan akan diriku. Atau mungkin juga kerana aku menyelitkan lebihan gaji agar dia boleh menyara keluarganya di kampung.
Aku pula mahukan pembantu kerana aku mahu kewujudanku disedari. Aku tidak mahu hidupku berakhir di rumah ini tanpa ada saksi. Tanpa ada sesiapa mengetahui. Aku melangkah dengan berhati-hati untuk mengelak Kiah, namun kami bertembung di ruang belakang.
“Puan..!” Kiah terjerit, segera menerpa ke arahku, terkejut melihat keadaanku yang berlumuran darah. “Saya panggil Mat, ya? Kami bawa puan ke hospital …”
“Jangan,” sanggahku. “Luka kecil saja …” tambahku, ingin melegakan perasaan cemasnya.
“Tapi … besar luka di kepala puan itu, perlu jahitan,” katanya, risau.
“Tidak apa, Kiah. Kau kan lebih tahu keadaan aku,” ucapku mengelak. Cepat-cepat aku masuk ke tandas.
***
Aku berbalas renungan dengan biasan bayangku yang menyedihkan di sebalik cermin.
‘Adakah malam ini kekal tanpa sudahnya?’ bisik hatiku, sedih.
Kubuang.
Kuabaikan.
Kutumpukan perhatian pada luka besar di dahiku.
Kubersihkan dan kututup dengan pelekat luka. Kesan kebiruan dan benjol besar akan timbul. Rasa sakitnya dapat kurasa hingga ke tengkorak kepala. Aku menggeleng. Kusisihkan kepahitan yang bertenggek di hatiku.
Detik itu ingin rasanya aku menangis, namun air mataku sudah enggan mengalir. Kesedihan ini sudah melangkaui batasnya. Sudah tepu rasanya. Aku bukan lupa untuk merasainya. Aku hanya tidak lagi mampu. Jiwaku sudah membeku.
Aku teringat kali terakhir aku benar-benar menangis ketika aku melepaskan ibuku pergi menghadap Ilahi. Ketika itu aku benar-benar rasa sedih. Aku juga menangis ketika aku dipaksa untuk menerima lelaki yang tidak aku cintai kerana alasannya agar kebajikanku terjaga apabila ibu dan abah sudah tiada.
Abah percaya bahawa suamiku jujur mencintaiku. Abah tidak pernah tahu dengan siapa dia meletakkan kepercayaannya. Aku masih mampu menangis selepas abah pergi menyusuli ibu. Walaupun dengan pemergian abah, semua hartanya jatuh ke tanganku seorang.
Orang berkata bahawa hidupku dilimpahi tuah dan keberuntungan. Aku ini ibarat tuan puteri yang lahir di atas tilam sutera, makan di atas dulang emas bersudu perak.
Ketika ini, melihat wajahku yang dipenuhi guratan luka dari balik cermin … wajah seorang wanita yang kalah dan diperhambakan.
Hidupku tidak lebih baik daripada Kiah. Malah lebih rendah lagi. Satu-satunya yang tidak pernah dilukai oleh suamiku adalah sepasang tanganku.
Syarikat besar, rumah besar dan segala-gala yang mampu aku miliki kini tidak akan lagi mampu membayar harga kebahagiaan untukku. Hidupku kini dikuasai oleh lelaki yang hanya mahukan hartaku, dan aku masih wujud kerana dia bergantung kepada tandatanganku. Detik itu juga aku teringat akan pesanan suamiku.
Aku tidak mungkin akan melupakan perintahnya. Bayaran persekolahan anak-anak manjanya yang tiga orang itu yang wujud mereka tidak pernah diketahui oleh arwah abah. Walaupun mereka tidak pernah menghuni rahimku, bertahun-tahun aku menanggung segala-galanya yang berkaitan dengan kehidupan mereka, termasuk melunasi biaya persekolahan mereka yang bukan murah … menghampiri lima angka. Mereka tidak menuntut ilmu di sekolah biasa seperti anak-anak gadis lain.
Walaupun aku sering dihina, disakiti dan dilukakan, aku masih mampu bertahan. Kenapa? Kerana aku menunggu hari ini. Hari di mana tuntutan perceraianku akan diserahkan oleh peguamku. Dia tidak akan terlepas kali ini selepas rakaman penderaan yang menyebabkan kematian janin dalam kandunganku kuserahkan kepada pihak polis.
Kali ini dia tidak akan terlepas. Kali ini aku akan bebas daripada ikatan hukum yang merantai takdirku. Inilah penghujung malam yang menabiri siangku.
***
Beberapa minit berlalu ketika suara Kiah menyelinap masuk dari celah pintu bilik air. “Tuan Syed sedang menunggu di ruang tamu …” katanya separuh berbisik ketika aku membuka pintu.
Kiah tersenyum ketika memandang wajahku … dan bajuku yang belum sempat kutukar.
“Baik!” ucapku lantas membuka pintu lebar-lebar.
“Puan, tadi saya sempat menghantar gambar puan kepada peguam puan …” Suara Kiah bersulam dengan keterujaan “Ada beberapa orang anggota polis menyertai Tuan Syed!”
Aku bergegas menuju ke ruang tamu.
***
Mungkin khabar yang dia terima pada hari itu terlalu berat untuk ditanggungnya. Dia yang masih berada di ruang makan rebah ketika kuhuraikan sebab kenapa peguam dan pegawai polis berada di rumahku, dan aku menerangkan perkara itu ketika dia sedang terbaring di katil hospital … tempat yang paling dibencinya. Malang sekali baginya, hari ini bacaan gula di dalam darahnya terlalu tinggi dan dia telah disahkan mengalami Diabetic stroke.
“Sayang … tolonglah, abang merayu! Beri abang satu lagi peluang ..” bisiknya berkali-kali.
Tetapi aku hanya tersenyum. Tegas. Dia harus keluar dari rumahku dengan kadar segera, berserta dengan anak-anaknya .. tanpa membawa apa-apa selain daripada pakaian yang melekat di tubuhnya.
“Kasihanilah abang! Bagaimana dengan hidup abang? Siapa yang akan menjaga abang?”
“Kenapa …?” soalku sepatah … lantas ketawa.
Ketawa, dan ketawa tanpa henti. Aku tidak tahu kenapa aku ketawa, tetapi aku rasa soalannya itu memasuki hatiku seperti ulat-ulat kecil yang bergerak-gerak menggeliat di celah nubariku. Aku rasa geli-geleman, dan aku terus ketawa.
Kerana aku sedang baik hati dan ingin bersedekah kepada keluarganya dengan kebarangkalian akan menarik tuduhan ke atasnya. Kerana aku tidak mahu dia meringkuk dalam tembok batu, dan aku tidak mahu membebankan pihak berwajib yang akan terpaksa merawatnya di dalam penjara.
***
Seperti rembesan sabar yang membanjiri kolah hatiku, akhirnya sinar bahagia menyebar … menyebak gelap malamku.