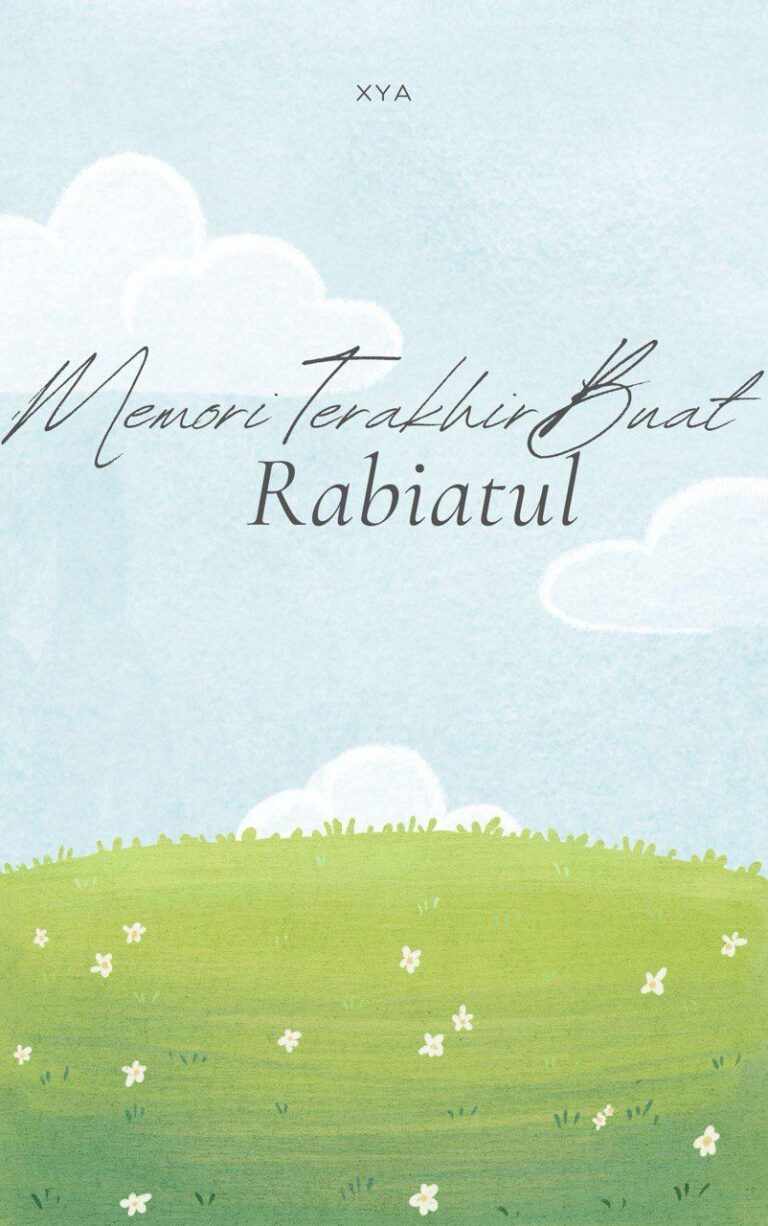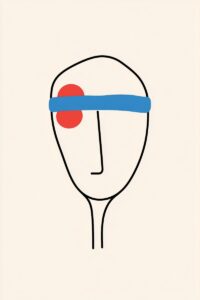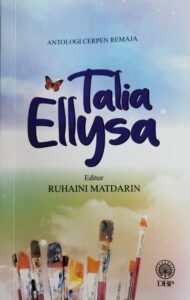ENGKAU pernahkah duduk bersendirian dan cuba mengenang kembali memori-memori gembira? Jika dikenang semula, indahnya waktu itu, bukan? Waktu ketika betapa polosnya kita untuk memahami sebuah erti kehidupan. Betapa polosnya kita kerana masih menganggap bahawa sebuah kasih itu akan berkekalan. Betapa polosnya kita menganggap semua memori gembira ini bakal sentiasa menjadi pengubat luka di jiwa. Dan, tanpa disangka memori indah itu telah berubah menjadi sebuah luka berdarah yang mencacatkan jiwa.
Ah, polosnya kita!
Bodohnya kita!
Sakitnya kita!
*
Azan zuhur sudah berkumandang. Matahari juga tegak berdiri di tiang langit. Teriknya pula membahang sehingga berasa seperti matahari itu sendiri yang datang mencubit kulit melebihi sedepa ini.
Namun, rasa panas ini bukan halangan buat dua orang cilik yang sibuk berkampung di tepi parit bersama kayu pancingan mereka. Baldi di tepi menjadi ruang khas simpanan ikan haruan hasil tangkapan mereka. Budak lelaki itu sibuk memasangkan umpan sambil mulutnya becok mengajar sahabatnya itu helah menangkap ikan haruan.
“Engkau faham tak ni, Bia?” soal Iman.
Rabiatul yang mendengar khusyuk dengan dahi yang berkerut, memandang tepat ke dalam mata Iman. “Tak. Aku langsung tak faham.”
Debap!
“Aduh! Sakitlah!” Jerit Bia.
“Tak guna betul! Dengarlah aku terang elok-elok ni!” marah Iman. Gadis kenit itu dijelingnya tajam.
Rabiatul mencebik. “Alah, engkau terangkanlah sekali lagi.”
“Ish … ini yang terakhir. Kalau engkau tak faham lagi, pandai-pandailah kaupancing ikan sendiri!” getus Iman.
Sekali lagi, Iman membebel dengan separuh tenaga. Setia mengajar sahabat sejatinya itu walaupun ikutkan hati, sudah lama diketuknya gadis berambut keriting itu.
“Macam ini ke?” soal Bia.
“Ha, reti pun. Sekarang engkau tinggal baling saja, lepas tu tunggu arahan aku. Kalau aku cakap tarik, engkau tarik.” Arah Iman membuatkan Rabiatul tekun mengangguk lalu menghumban umpan dengan kemas. Tangannya erat memegang kayu pancing itu.
Hari ini, Rabiatul tekad mahu menangkap ikan haruan! Jiwanya berkobar-kobar apabila melihat enam ekor ikan haruan milik Iman yang sibuk berkocak di dalam baldi. Dia mahukan ikan itu! Dia mahu menjadi seperti Iman!
“Okey, Bia! Tarik!!!” Jerit Iman.
“Iman Asyraf! Rabiatul Adawiyyah!” Pekikan itu membuatkan langkah Iman dan Rabiatul terkunci seketika. Perlahan-lahan mereka menoleh.
Kelihatan gerangan seorang wanita yang bernafas berat sedang merenung tajam ke arah mereka. Sebelah tangannya erat memegang sebatang penyapu. Wajahnya mencuka dengan dahi yang berkerut seakan-akan raksasa yang benar-benar hauskan mangsanya. Mak Dah perlahan-lahan mengatur langkah dengan “senyuman” di bibir. Jelas api membahang di atas kepalanya, serupa benar dengan cuaca panas terik sekarang!
“Bertuah punya budak! Kau orang mari sini! Amboi, lepas sedap-sedap habiskan kek aku, di sini kau orang melepak?! Sini kau! Sini! Hoi, nak lari ke mana tu?!”
Kayu pancing dan baldi habis dibuang entah ke mana. Bersama tawa yang separa gerun dan teruja, Iman tarik tangan Rabiatul bersama langkah yang besar. “Pecut, Bia! Pecuuut!!”
Kekek tawa Iman dan Rabiatul bersatu membuatkan suasana semakin meriah. Jeritan garang milik Mak Dah menambah lagi perasa sehingga orang-orang kampung yang melihat hanya mampu tersengih kerana sudah masak dengan kerenah dua orang budak yang tak habis-habis mengusik wanita yang hampir menjadi separuh abad itu.
*
‘Ah, seronoknya!’ Itu bisikku tatkala melihat dua kanak-kanak yang sedang berlari tanpa menghiraukan suara dunia.
‘Aku mahukannya kembali.’ Dadaku tiba-tiba berasa dihimpit dengan batu yang besar. Aku tenung kanak-kanak yang sedang berlari itu dengan seribu perasaan. Kotak suaraku seakan-akan terbakar menahan semua raungan.
‘Ya Allah. Aku mahukan rasa ini kembali’. Aku terduduk, mahu menggapai tangan kecil kanak-kanak itu. Air mata yang tertahan akhirnya tertumpah dan tidak berhenti bercucuran jatuh ke pipiku. Bibirku tidak berhenti menjerit dan menyeru nama yang bertakhta keras di hatiku.
‘Aku merayu … kembalikanlah memori ini semula.’ Rintih hati Bia.
*
Allahuakbar! Allahuakbar!
Azan subuh berkumandang itu menyentakkan aku daripada tidur lenaku. Pelihatanku berasa kabur tapi, aku usap saja air mata ini dengan rasa tak berdaya. Perlahan-lahan aku bangun, mengambil wuduk sebelum menunaikan kewajiban sebagai umat Islam. Setelah itu, aku ambil al-Quran dan surah Yasin dibisikkan lembut.
Sudah hampir dua minggu berlalu setelah Iman dikebumikan. Iman pergi akibat kelalaian pemandu kereta bertentangan yang asyik bersama air mabuk di tangannya.
Iman, sahabat sayangku yang aku tunggu penuh dengan sebuah penantian setelah bertahun-tahun belajar di negara orang sana. Akhirnya pulang ke kampung dengan kain kapan melilit seluruh tubuhnya.
Iman, sahabat aku. Nyawa aku. Pergi kerana manusia yang langsung tidak bertanggungjawab. Aku menghela nafas panjang sebelum menyusun kembali al-Quranku di atas rak. Kotak besi yang bercorak bunga kecil itu diambil dan dibuka. Berkepuk, berpuluh-puluh surat dalam kotak besi itu. Kemudian, aku ambil satu per satu surat yang masih terkunci bersama sampulnya.
Ini surat terakhir daripada Iman. Bukti pengakhiran kisah buat kami berdua. Pengakhiran memori berharga buat kami berdua. Epilog kisah kami yang tak mampu akan aku akhiri. Aku tersenyum pahit. Surat itu aku belai penuh kasih sebelum aku dakap erat.
Imanlah yang mencadangkan agar kami berbalas khabar melalui surat berbanding menggunakan gajet kecil mewah itu. Awalnya, aku tak berpuas hati, berbalas surat itu terlalu mengambil masa yang lama. Aku tak larat mahu menunggu tapi, aku mengalah saja apabila mendengar pujukannya.
Bukankah memori akan jadi lebih berharga kerana setiap detik yang kita nantikan itu?
Aku telan kata-kata penuh kaca itu dengan sebak di jiwa. Aku cuba tahan esakan terlepas dari bibir.
‘Iman … Iman … Aku rindu … Aku rindukan kau … .’ Rintih hati Rabiatul.
“Tok! Tok! Tok!”
Bunyi pintu terkuak setelah bunyi ketukan berkali-kali. Wajah Rahima, kakakku tersembul di sebalik pintu bersama senyuman segaris.
“Bia, Mak Dah datang. Dia nak sampaikan sesuatu untuk engkau.” Ucap kakak.
Aku sambut dan cium tangan berkedut Mak Dah. Dulu, wanita yang sentiasa bersemangat berlari semata-mata mahu menarik telinga aku dan Iman kini, hanya mampu terbongkok-bongkok bersama senyuman hambar di bibirnya. Wajahnya sedikit pucat dan cengkung. Mak Dah yang kehilangan anak kesayangannya itu ternyata masih bersedih.
Mak Dah usap tanganku dengan mata yang berkaca. Pipiku dicium bertalu-talu sebelum membisikkan. “Bila Mak Dah tengok muka kamu, Mak Dah berasa seperti Iman masih hidup.”
Ah, hampir saja aku hancur apabila mendengar ayat itu! Mataku laju berkelip menahan air mata daripada melimpah. Aku hanya tersenyum kelat.
“Mak Dah tak mahu berlama-lama di sini sebab Mak Dah tahu Bia juga masih berasa sakit dengan kehilangan Iman. Tapi, Mak Dah nak sampaikan sesuatu yang Iman tak mampu untuk sampaikan,” ujar Mak Dah lalu mengarahkan anak buahnya untuk membawa sebuah kotak kecil kepadanya.
Kotak itu dibuka dan satu barang perhiasan jelita berkilau menerjah pandanganku membuatkan aku tergamam. Jantungku berdegup laju. Tubuhku berasa berat dan ringan dalam masa yang sama. Aku telan esakan yang semakin kuat mencengkam dadaku. Aku terus mendongak melihat wajah Mak Dah, meminta sebuah penjelasan.
Seakan-akan memahami rasaku, Mak Dah menggenggam erat kedua-dua tanganku. Jari manisku diusap.
“Sehari selepas Iman pulang, sepatutnya cincin ini tiba ke jari manis milik kamu, Bia.”
Tatkala mendengar itu, duniaku berasa seakan terhenti. Aku bungkam. Seluruh tubuhku bergetar.
“Iman cintakan Bia.”
Tiada yang mampu aku katakan.
“Ah … Ah …” hanya erangan sakit yang keluar. Kali ini, tiada lagi yang mampu aku pertahankan. Dinding hatiku hancur berkecai hanya kerana tiga perkataan sakti itu. Jiwaku habis disiat dahsyat. Raunganku akhirnya keluar nyaring penuh dengan sebuah penyesalan.
“Iman aku … Iman aku … . ”
“Nyawa aku … Jiwa aku … .”
“Iman aku … .”
*
Bia, aku dapat ikan!
Bia, Pak Samad ada jual aiskrim keladi hari ini!
Bia, mak aku ada masak lauk lebih! Jomlah datang! Makan bersama-sama dengan aku!
Bia!
Bia!
Bia … janganlah menangis macam ini … .
Aku janji! Kalau aku balik, kaulah orang kedua yang akan aku cari! Yang pertama, mestilah mak aku, kan? Haha!
Bia … tunggu aku balik, janji?
“Ya Allah, tolong aku. Aku tak sanggup. Nyawa aku, nyawa aku sudah hilang. Sakit sangat, ya Allah. Sakit sangat. Tolong aku … tolong hambamu yang kerdil ini.”
“Iman … .”
“Bia mahukan Iman … .”
*
Ke hadapan Rabiatul Adawiyyah yang berada jauh nun di tanah Melayu sana.
Untuk makluman engkau, kali ini surat aku panjang sedikit, tahu? Aku tahu engkau pemalas tapi, ada perkara penting yang aku nak sampaikan. Jadi, tolong jangan malas dan rajin-rajinkanlah diri membaca sampai ke akhir surat ini.
Ikut pengiraan aku, surat ini sepatutnya tiba semasa aku dalam perjalanan pulang ke Malaysia. Aku harap surat ini tiba tepat pada masanya.
Bia, sahabat tercintaku.
Aku berharap saat matamu menjamah isi surat ini, kaumasih lagi boleh tertawa dan tersenyum seperti sediakala. Aku berharap, kaumasih lagi sihat dan bersemangat untuk meluah segala rasa ketika aku tiada di sisimu sekarang.
Aku … ada sesuatu yang amat penting ingin aku sampaikan. Melibatkan hubungan persahabatan dan rasa cinta yang terbit berbunga dari hatiku.
Rabiatul Adawiyyah,
Aku cinta kau.
Maaf, mungkin agak kelihatan seperti pengecut kerana meluahkan perasaanku melalui surat tetapi, aku benar-benar mahu menulis surat ini demi melakar detik-detik memori bahagia kita.
Secara jujurnya, aku tidak tahu sudah berapa lama jiwaku ini mula mendambakan cinta daripadamu tapi, perasaan ini sudah wujud sehingga membuatkan aku sesak dan gerun.
Jadi, aku berdoa kepada Allah. Aku meminta petunjuk daripada Allah.
Adakah perasaan ini benar-benar ikhlas atau hanya ilusi dari jiwaku semata?
Tapi semakin lama, semakin dalam rasa cinta ini sehingga membuatkan hatiku meluap-luap kesakitan. Hatiku benar-benar mahukan engkau sentiasa berada di sisiku.
Bia.
Aku sudah tidak sanggup menahan rasa kasih yang mendalam ini jadi … sudikah engkau untuk menikahi aku?
Sudikah engkau untuk menempuhi segala rintangan masa hadapan yang terlalu kabur ini bersama selamanya dengan aku?
Rabiatul Adawiyyah, nyawa hidupku.
Sudikah engkau menerima rasa sayang persahabatan yang kukuh ini berubah menjadi perasaan cinta fitrah yang diturunkan oleh Tuhan?
Sudikah engkau, Rabiatul Adawiyyah? Untuk berada disisiku? Walaupun maut datang menjemput kita terlebih dahulu?
Sudikahkau?
Sahabat yang Mencintaimu,
Iman Asyraf.