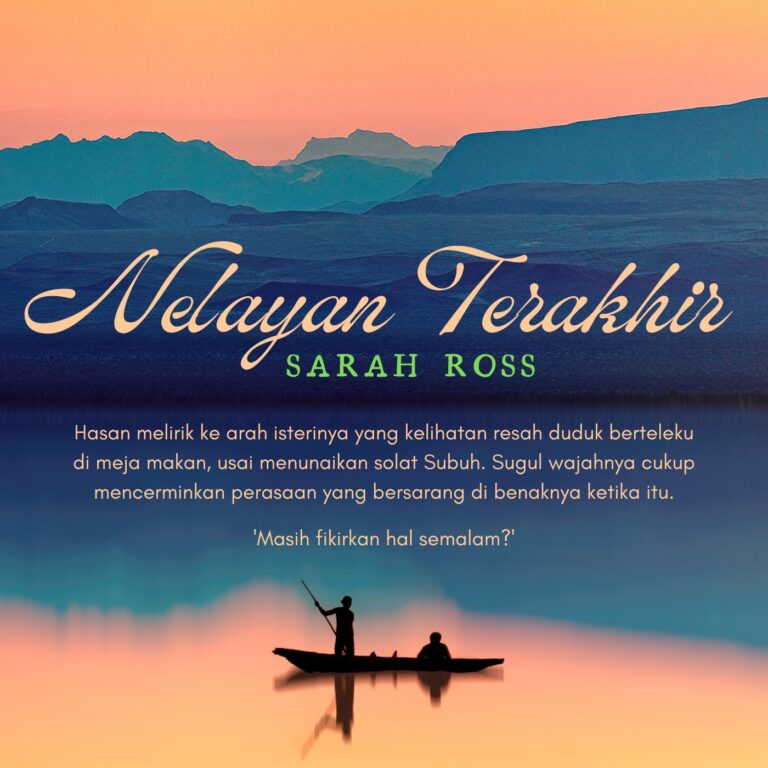HASAN melirik ke arah isterinya yang kelihatan resah duduk berteleku di meja makan, usai menunaikan solat subuh. Sugul wajahnya cukup mencerminkan perasaan yang bersarang di benaknya ketika itu.
‘Masih fikirkan hal semalam?’
Hasan bertanda tanya sendiri. Jala yang tersidai di sampiran diangkat lalu disangkutkan ke bahu. Kepalanya lengkap disarungkan topi dan tangan kiri menjinjing baldi.
“Ina!” laungnya dari muka pintu setelah menyarung selipar. “Cepatlah, nanti kesiangan pula.”
Zalina segera bangkit. Bekal mangkuk tingkat yang disediakan sebelum Subuh tadi dicapai.
“Zaid, keluar nanti jangan lupa kunci pintu ya,” pesannya kepada anak sulung yang sedang menuntut di tingkatan lima itu. Sebentar lagi keenam-enam anaknya akan berjalan kaki ke sekolah.
Zalina akur membuntuti suaminya dengan wajah berpalit kelat. Langkahnya longlai seperti sayur yang ketandusan air. Semangatnya tidak ubah seumpama tanah yang kering kontang.
“Isy, awak ni! Kita keluar nak mencari rezeki. Nanti ikan pun takut nak lekat tengok wajah awak yang kelat pekat,” tegur suaminya.
“Saya risaulah, abang.” Kerut di dahi kian jelas jalurnya. “Saya tengok abang tenang saja. Tak risau?” soal Zalina.
Kelihatan beberapa nelayan lain sedang menolak bot ke kaki air. Perkampungan nelayan Tanjung Telok Tempoyak sayup-sayup ditinggalkan.
Hasan mengemudi perjalanan membelah lautan luas demi secupak rezeki yang halal. Seluas itulah harapan ditadah sebaik menjauhi daratan. Di sini lubuk rezeki buat keluarga, meski diuji ombak dan badai yang terkadang nakal menyapa.
Cuaca pagi itu menyebelahi mereka meski tadi malam diselimuti lebat hujan. Rembang jingga sejalur dua menjalar di dada langit berdikit-dikit sebelum mengembangkan siang hari.
“Apa yang awak risaukan sangat?” Hasan tekun mengemudi ke tempat yang lebih dalam dan terdapat banyak ikan.
Dia menghirup bau laut. Bau itu adalah harum jati dirinya. Di sini taman permainannya sebaik meninggalkan buaian dan dodoian ibu. Dia tidak mengenal bau yang lebih memukau dari bau laut. Dengan bau inilah dia menumbuhkan dewasa, mengakar peribadinya.
Pernah arwah ayahnya berpesan, “Hasan, kalau engkau takut dilambung ombak, jangan berani berumah di tepi pantai. Di sini hanya orang-orang yang kuat, menemukan kehidupan.”
“Abang, anak-anak kita masih bersekolah. Banyak perlukan duit. Zaid tu, tahun depan akan ke universiti pula. Bukan sedikit belanjanya nanti. Mana kita nak korek duit, abang? Simpanan pun tak ada. Kalau ada seurat dua emas, bolehlah saya gadaikan.”
“Isy, awak ni mengeluh bersuamikan saya, ke? Awak pun tahu, saya memang tak mampu nak beri awak kemewahan.”
“Ke situ pulak, abang ni! Maksud saya, saya nak tengok anak-anak kita berjaya macam anak Lebai Bidin tu. Berderet-deret masuk universiti. Habis belajar, dapat kerja yang elok dan gaji pun bagus. Tidaklah kais pagi makan pagi, kais petang makan petang macam kita ni, abang.”
“Bukankah kata Azman, khabar tu baru ura-ura?” Hasan mematikan enjin bot sambil menunggu sauhnya berlabuh. Jala dirapikan sebelum dihampar ke dada air.
Semalam, sewaktu para nelayan menyerahkan hasil tangkapan kepada peraih, Azman telah memanggil mereka untuk mengadakan pertemuan tergempar.
“Begini, aku dengar, kerajaan negeri akan menjalankan satu projek mega di perairan kita ini,” beritahu Azman.
“Khabarnya, projek tambakan untuk membina tiga buah pulau buatan di selatan negeri!”
Allah! Ketat dada Zalina dijerut khabar dukacita itu. Tidak betah membayangkan kesan buruk yang bakal menghimpit nasib lebih lima ribu nelayan pantai di pulau ini.
Projek tambakan demi tambakan yang dilaksanakan sejak lima dekad lalu telah sedia menjadi penyebab pendapatan mereka terjejas teruk. Hasil tangkapan ikan, udang, ketam dan sotong kian berkurangan.
Adakala, mereka hanya beroleh kurang dua kilogram ikan dan beberapa ekor udang serta ketam. Betapa sulitnya keadaan yang menghimpit, apatah lagi jika projek tambakan baru dijalankan.
“Mereka tidak fikirkan ke kesulitan kita sebagai nelayan?” keluh Pak Mail yang berusia senja. Hidupnya bergantung penuh kepada hasil laut.
“Mengapa mereka tamak sangat? Bagaimana kita mahu hidup jika lambakan lumpur menyebabkan ikan-ikan lari ke laut dalam? Kita mahu makan apa? Pasir?” Jali melontarkan kemarahan. Hatinya berbungkus sebal.
Hasan menarik jalanya perlahan-lahan. Sedikit kecewa kerana tiada seekor pun hidupan laut yang sangkut di jaringnya.
“Abang, kalau tiada angin, takkan pokok bergoyang!”Zalina tidak percaya itu sekadar cakap-cakap kosong. Tidak ada kepentingannya untuk mengacah para nelayan dengan berita yang diibarat menabur pasir ke periuk nasi mereka.
Hasan menebarkan jala sekali lagi. Mulutnya terkumat-kamit membaca doa yang kemudian disambung dengan zikir pembuka rezeki.
“Kita bergantung dan meminta pada Tuhan. Bukan kepada makhluk,” nasihat Hasan. Wajahnya masih tenang, setenang air laut yang menyerakkan rona kebiruan.
Zalina menarik nafas panjang. “Saya tahu abang, kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, tetapi kita masih diberi akal untuk berfikir dan kudrat untuk bertindak. Kita tak boleh biarkan nasib kita bagai telur di hujung tanduk.”
“Bercakap dengan awak ni, mana pernah abang menang,” gurau Hasan sambil tertawa kecil. Isterinya itu ibarat pakar ekonomi. Sesekali hujahnya tidak ubah seperti ahli politik.
Bukan dia tidak gusar, bukan dia tidak dilambung bimbang. Perkara itu masih dalam kajian dan perbincangan kerana belum ada pengumuman rasmi dibuat. Risau berlebihan juga tidak membuahkan manfaat.
“Bertenanglah. Kita ada Dia sebagai tempat mengadu,” nasihat Hasan kepada isterinya.
Setelah beberapa tarikan jala berhasil, mereka duduk berehat sambil menjamu selera. Nasi lemak berlaukkan telur mata kerbau itu terasa begitu enak dinikmati di tengah lautan. Sayup-sayup kelihatan sebuah bot datang menghampiri.
“Eh, Kak Munah! Marilah makan sama,” pelawa Zalina. “Saya bawa nasi lemak ni.”
“Rajin Ina masak. Kak Munah bawa nasi goreng saja.”
Zalina menghulurkan sepinggan nasi lemak kepada Kak Munah. Wanita berusia lebih tujuh tahun daripadanya itu merupakan ibu tunggal. Pundaknya menggalas tanggungjawab sebagai ibu dan ayah kepada tiga orang anak.
“Anak-anak sihat, kak?” tanya Zalina berbasa-basi. Sebenarnya dia mahu bertanyakan pendapat Kak Munah berkaitan isu projek penambakan baharu itu.
“Alhamdulillah, mereka sihat,” jawab Kak Munah. “Sedap sangat nasi lemak Ina masak ni. Kalau tak ke laut, bolehlah Ina berniaga nasi lemak. Tambah beberapa jenis lauk, mesti laku keras!” Zalina terdiam mendengar usul Kak Munah kepadanya.
“Kak Munah, agak-agaknya, kita ni generasi nelayan terakhir di pulau ni? Selepas kita, tak ada pelapis yang menyambung kerja kita ni?” Sekali lagi Zalina menyuarakan kebimbangannya. Kebimbangan seorang ibu memikirkan masa depan anak-anak yang bergelut dengan gelombang ketamakan manusia.
Usai makan, pandangan Kak Munah memintal gelombang lautan luas di hadapannya.
“Kita ini bilis, Ina. Biarlah berenang bersama bilis. Kalau berani ke tempat jerung, kita bakal dimakannya.”
Dia sedar, projek itu bakal memusnahkan ekosistem marin dan alam sekitar yang seterusnya akan mengambus lubuk rezeki mereka. Dalam pertemuan ringkas semalam, mereka telah pun sepakat melantik Azman sebagai wakil para nelayan untuk mengemukakan petisyen bantahan terhadap projek penambakan tersebut.
“Kalau pun kita menjadi nelayan terakhir, bukan bererti hidup kita terhenti di sini,” ujar Kak Munah.
“Takdir Tuhan tidak pernah kejam. Jika bukan rezeki kita di laut atau di udara, pasti ada secubit di daratan.”
Sekali lagi Zalina terdiam. Dia mengakui kebenaran kata-kata Kak Munah. Wanita itu mendapat julukan wanita besi kerana kegigihannya membesarkan anak-anak sendirian.
Ketika anak bongsu memanjat usia empat tahun, takdir Tuhan memanggil suaminya pulang ke pangkuan. Pun begitu, dia tidak mudah rebah atau mengenal putus asa. Dia bangkit meneguhkan pasak kedua kaki untuk menopang masa depan anak-anak di pundaknya.
Semasa musim angin kencang, Kak Munah tidak turun ke laut. Sebaliknya dia akan mengambil upah memandu lori atau mesin foklif. Sudah lebih 10 tahun dia memegang lesen memandu kenderaan angkut barang itu. Selama itu jugalah dia mengambil upah sebagai pemandu sambilan demi memenuhi kebutuhan keluarga.
Sayup-sayup kedengaran suara memecah keheningan. Walau pun samar-samar, mereka percaya itu suara manusia.
“Tolong!”
Sekali lagi suara itu menjamah telinga sekali gus menguatkan keyakinan mereka. Pantas Kak Munah menghidupkan enjin menghala ke arah suara yang didengar tadi. Hasan berbuat hal yang sama, membuntutinya.
Tidak sampai dua pelaung dari situ, mereka melihat seseorang tenggelam timbul dengan tangan terkapai-kapai.
“Eh, Hamzah tu!” teriak Hasan. Dia melepaskan topi dan bersedia untuk terjun.
“Nanti! Pakai jaket ni dulu.”
Kak Munah mencapai jaket keselamatan di dalam botnya yang memang sentiasa dibawa bersama-sama. Menunggu Hasan mengenakan jaket itu ke badan, pantas Kak Munah melambakkan ikan yang tersimpan di dalam tong. Dia mengikatnya dengan tali lalu dicampakkan ke arah Hamzah yang sedang bergulat dengan ajal.
“Pegang tong tu!” jeritnya.
Hasan turun mencebur ke perut air. Lincah ayunan tangan dan kakinya menghampiri Hamzah, memaut dada dan menyokong kepalanya naik ke permukaan.
Tong yang dipaut Hamzah ditarik oleh Kak Munah. Tubuh Hamzah yang longlai dicapainya. Dengan bantuan Hasan, Hamzah dibawa naik ke atas bot. Hasan dipandu untuk segera memberikan bantuan kecemasan. Dia pernah mengikuti kursus pertolongan cemas yang dianjurkan oleh Persatuan Wanita Perkasa satu ketika dahulu.
Hamzah berjaya memuntahkah sebahagian besar air laut yang tertelan olehnya. Hasan membantunya duduk bersandar di dinding bot.
“Terima kasih,” ucapnya dalam nada perlahan.
Naik turun desah nafasnya mengisi keheningan. Setelah keadaannya beransur baik, Zalina menghulurkan secawan air teh suam. Hamzah meneguk perlahan-lahan. Tenaganya yang hilang perlu segera dipulihkan.
“Terima kasih Hasan, Kak Munah, Ina. Terima kasih,” ucapnya berkali-kali.
Tiada perkataan yang lebih baik untuk menghargai kebaikan mereka selain ucapan terima kasih dan doa kebaikan yang dipanjatkan kepada Tuhan. Ternyata Allah SWT masih merezekikan sepotong nyawa untuknya meneruskan kehidupan. Masih diberi peluang kedua kali untuk memperbaiki persiapan pulang.
“Bot kau karam?” tanya Hasan.
Hamzah mengangguk. “Aku tak perasan bot aku bocor. Bila air dah masuk dan menenggelamkan belakang bot, baru aku tersedar.” katanya dengan nafas yang tersekat-sekat. Nafasnya masih belum pulih sepenuhnya.
Dia terpaksa berenang lama untuk menghampiri pantai, tetapi tajam gelombang tidak memihak kepadanya menyebabkan tubuhnya semakin menjauh.
Setelah hampir hangus seluruh tenaganya, tidak semena-mena, otot kakinya pula diserang kekejangan. Hamzah tidak betah mengalah begitu sahaja. Berpantang maut sebelum ajal!
“Hasan, lain kali, hati-hati ya. Orang yang hampir lemas akan memaut dan menekan apa-apa yang tercapai olehnya. Termasuklah orang yang nak selamatkannya,” pesan Kak Munah.
Hasan akur akan kecuaiannya. Hamzah pula memohon maaf jika perlakuannya tadi mendatangkan mudarat kepada Hasan.
“Marilah kita pulang. Kami bawa kamu ke klinik, ya?” Mereka memutuskan untuk segera membawa Hamzah pulang biar pun hasil tangkapan hari itu baru sedikit.
Jika mereka ditakdirkan menjadi nelayan terakhir, mereka mahu menjadi nelayan yang terbaik. Nelayan yang memiliki jati diri tinggi, yang berbudi dan berbakti. Mereka berikrar dengan sesungguh hati!