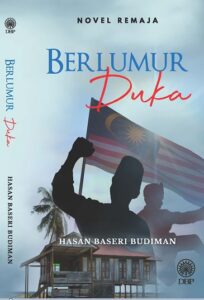SUDAH puluhan tahun sawah itu ditinggalkan terbiar. Usang dan kontang. Kini, hanya semak samun dan binatang-binatang berbisa sahaja yang menghuni di situ. Apatah lagi setelah kedua-dua orang tuaku telah tiada. Sepi terbiar.
Dahulu, di sawah itulah jadi tempat permainanku sewaktu kecil. Pantang cuti sekolah, sawah itu akan riuh rendahlah dengan suara-suara jeritan kami, bermain bersama adik-beradik, anak-anak jiran dan juga saudara mara di kampung.
Pendek kata suasana waktu itu sungguh meriah. Sambil membantu ibu bapa menanam dan menuai padi, kami juga akan berkelah beramai-ramai di bawah pondok yang didirikan oleh ayah di tepi sawah.
Ketika itu, asyik sekali melihat orang-orang meliuk-lintuk, menari di tengah sawah sambil menikmati elusan bayu.
Selalunya di tepi pondok kami, emak dan ayah akan bercucuk tanam, sementara menunggu padi masak untuk dituai. Apabila padi ranum dan tiba musim menuai, hasil tanaman yang ditanam itu akan dapat dipetik dan dimasak.
Selain itu, sayur yang dipetik itu juga diagihkan kepada jiran tetangga dan saudara mara. Begitulah kebiasaannya budaya hidup di kampung. Sungguh meriah dan harmoni.
Sifat tolong-menolong dan bergotong-royong bagaikan sudah mendarah daging dan sebati dalam jiwa. Kami menjalani hidup bermasyarakat dengan makmur. Sikap tolak ansur telah tertanam dalam diri masing-masing, sebagai anak kampung.
Aku hanya mampu mengenang kembali nostalgia mengemping padi apabila tiba musim menuai. Waktu itu, kami hanya menggunakan lesung kaki buatan ayah. Lesung indik itu diletakkan di bawah bangsal di belakang rumah.
Ketika itu, beras tidak pernah sesekali dibeli. Untunglah! Kerana kami dilahirkan menjadi generasi yang mengenali erti susah payah menanam dan menuai padi dengan keringat sendiri.
Mengenali pokok padi dan jerami. Daripada setangkai padi, aku meraup kesyukuran hidup menjadi seorang anak desa yang mengisi perut dengan percuma.
“Mahalnya”.
“Berapa harga?”
“RM38 ringgit untuk 10 kilogram beras putih tempatan.”
“Wow, ini mencekik darah namanya!”
Sambil menolak troli barang bergerak ke hadapan, sepasang suami isteri itu berlalu meninggalkan rak beras di pasar raya itu dengan perasaan jengkel dan hampa.
Aku hanya mendengar perbualan suami isteri itu di hujung-hujung telingaku sambil membelek-belek sekampit beras putih tempatan berharga RM28 untuk 5 kilogram. Nampaknya semua harga melambung naik. Disebabkan tiada pilihan, aku beli sekadar mampu.
“Jadilah, janji boleh makan,” getus hatiku sendirian.
Sebelum bergerak pergi, aku jua sempat menoleh ke arah troli pasangan suami isteri itu tadi. Tidak banyak barangan di dalam trolinya. Barangkali mereka juga sedang berkira-kira untuk membeli susu dan lampin untuk anak kecil yang sedang dipangku oleh si isteri.
Jauh di sudut hati aku berasa amat simpati. Kenaikan harga barangan keperluan asas semenjak kebelakangan ini, sungguh menyeksakan bagi keluarga yang mempunyai tanggungan besar.
Keadaan ini amat mengesankan kehidupan golongan bawahan dan berpendapatan rendah. Apalagi jikalau hidup di kawasan bandar besar dengan kos sara hidup yang semakin meningkat. Malah keadaan ini mungkin boleh menjadi punca keretakan rumah tangga kerana masalah kewangan yang menggugat.
Teringat pula aku kepada arwah Pak Long Jawa, apabila suatu hari mereka duduk bersembang kosong di beranda rumah bercerita tentang kehidupan anak cucu masing-masing.
“Aku bimbanglah Pak Njang, andai kata tiga puluh tahun atau empat puluh tahun lagi, padi dan beras menjadi terlalu mahal. Bagaimanalah agaknya nasib dan masa depan anak cucu kita nanti?”
Ujar Pak Long Jawa, sekadar meluahkan kebimbangannya kepada legasi yang bakal ditinggalkan suatu hari nanti. Kegusarannya terhadap harga getah yang terlalu rendah, merayap jua kepada keadaan harga barang yang kian melonjak.
Aku melihat ayah menarik nafas panjang sambil merenung jauh. Seperti sedang memikirkan apa yang diluahkan oleh Pak Long Jawa sebentar tadi. Tiada jawapan yang terlontar dari bibir ayah.
Sekarang, kebimbangan Pak Long Jawa suatu masa dahulu, benar-benar telah menjadi kenyataan. Kini, kami telah mengharunginya. Tidak boleh tidak, hidup tetap perlu diteruskan. Walau apa pun perubahan yang berlaku.
Ini zaman anak-anak muda tidak lagi boleh mengharapkan keringat tua ibu ayah di kampung untuk membanting tulang turun ke sawah.
Ini zaman anak-anak muda perlu bergerak pantas dan lebih jauh lagi, agar berdaya saing untuk memajukan diri dengan melakukan perubahan.
Krisis ekonomi dan keperluan asas seharusnya membuka mata semua generasi agar mengutamakan keperluan berbanding kehendak.
Berbelanjalah mengikut kemampuan diri sendiri. Utamakan yang lebih penting. Jangan sesekali mengikut gaya hidup orang lain sehingga berhutang keliling pinggang, lantaran, saiz pakaian kita amat berbeza.
Dengan keadaan ekonomi yang kian merudum, fenomena masa kini telah jauh berubah. Kebanyakan pasangan tidak lagi betah duduk diam di rumah. Mereka harus keluar bekerja demi kelangsungan hidup untuk menanggung nafkah keluarga dan keperluan diri.
Pendapatan kecil yang dicatu-catu itulah yang akan membuatkan rumah tangga dan kasih sayang mereka bertahan atau bukan dengan suhu ekonomi yang begitu suram.
Seketika bahuku ditepuk. Anis, anak saudaraku sudah tercegat di sebelah. Rupa-rupanya sudah lama dia menunggu dan memerhatikan karenah pelanggan yang membeli belah di pasar raya itu termasuk aku.
“Dah bayar?
“Belum.”
“Cepat pergi kaunter sebelum orang ramai beratur,” ujarnya.
Tanpa berlengah aku terus bergegas membawa sekampit beras ke kaunter bayaran.
“Terima kasih. Datang lagi.”
Ucap juruwang yang bertugas sambil memulangkan wang yang berbaki hanya beberapa ringgit saja. Sebaik sahaja selesai urusan pembayaran aku menuju ke kereta tempat Anis menunggu.
“Tak ramai orang hari ni. Pasar raya lengang,” kataku, mengomel kecil.
“Orang berjimat-cermat Mak Su. Harga barang kian mahal. Kuasa beli semakin kurang,” balas Anis.
Aku mengangguk tanda faham. Sebentar kemudian kereta bergerak keluar meninggalkan pasar raya. Sepantas kereta bergerak, begitulah ligatnya fikiranku berputar memikirkan apa lagi yang akan naik selepas ini.
Sebagai rakyat marhaen, apalah daya kami untuk memprotes segala ketidakpuasan hati, jika itu sudah ditetapkan. Para peniaga juga terpaksa akur, agar tidak menanggung kerugian yang besar.
Namun begitu, ada juga para peniaga yang sengaja mengambil kesempatan untuk menaikkan harga dengan menyorokkan barangan subsidi. Begitulah keadaannya.
Sekampit beras putih tempatan yang dahulunya menjadi makanan rakyat marhaen, kini sekelip mata sudah bertukar menjadi beras kayangan yang mengisi perut dengan sajian sepinggan sengsara.
Pandanganku yang tertumpu pada sawah yang tadinya indah menghijau, kini telah bertukar menjadi kontang dan gersang bersama sebuah harapan yang telah kabur dan sirna.
“Kenaikan harga sayuran menjelang Disember, meningkat seratus peratus akibat musim tengkujuh!”
Paparan berita dalam talian sebuah akhbar perdana, yang memaklumkan kenaikan demi kenaikan itu terus-menerus buat aku terpana. Tiada kata mampu terluah. Rakyat semakin parah!