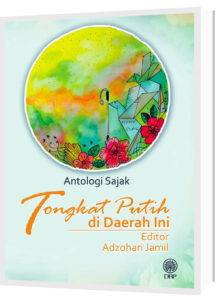Cerpen ini mendapat Johan dalam Sayembara Menulis Cerpen bersempena dengan Dekad Bahasa Kebangsaan 2024,
Peringkat Negeri Kedah
—
MALAM kian pekat. Bulan dan bintang tidak kelihatan. Hanya sesekali angin berhembus menyapa pipi. Namun tetap tidak mampu menyejukkan hatinya yang kepanasan. Benarlah kata orang, lidah lebih tajam daripada mata pedang. Kata-kata Halim terngiang-ngiang di cuping telinga seolah-olah rakaman audio yang diulang-ulang tanpa jeda. Bingit di telinga, perit di jiwa.
“Aku tak puas hati dengan Heng. Dia selalu ambil kesempatan atas kesempitan hidup orang kita. Cuba kamu fikir. Dia beli serkap Pak Mael pada harga yang murah. Kemudian, dia jual semula pada harga yang tinggi. Itu untung atas angin namanya!” suara Halim kedengaran di seluruh warung Mak Minah.
Saya yang duduk membelakanginya hanya mendengar dengan hati yang terbakar. Tuduhan yang dilemparkan Halim terhadap papa benar-benar keterlaluan. Namun, saya tidak berdaya untuk bersuara. Apatah lagi berdebat dengan sosok yang di dadanya penuh rasa benci dan tidak puas hati. Bukankah perbuatan itu tidak ubah seperti hendak meluruskan ekor beruk?
Dahulu, dia terkenal sebagai seorang pemuda yang berjiwa idealis, penuh wawasan dan keinginan untuk mengubah negara dan bangsanya. Kata orang, dia seorang pemimpin mahasiswa yang lantang bersuara. Dia pernah menangguhkan pelajaran kerana digantung pengajian akibat menyertai satu demonstrasi haram di ibu kota. Mujurlah, tempoh dia digantung pengajian hanya satu semester.
Kini, dia kembali ke kampung tetapi bukan untuk menumpahkan bakti. Sebaliknya, dia hanyalah penganggur terhormat yang menyebarkan benci. Tatkala mendengar cercaan yang Halim lemparkan kepada papa, terbit rasa geram yang teramat. Malah, tiada lagi rasa hormat yang tersisa.
Saya tidak nafikan bahawa proses penghasilan serkap amat rumit. Bahkan, saya dan papa pernah mengikuti Pak Mael masuk ke dalam hutan mencari buluh duri, rotan dan akar pukang untuk dibuat serkap. Hanya buluh yang benar-benar matang ditebang dan dibawa pulang. Proses membelah dan meraut buluh juga amat rumit kerana perlu memastikan ukuran setiap bilah buluh itu sama besarnya. Jika tersilap langkah, boleh terluka jari-jemari.
“Setiap batang buluh ini, kita kena gosok dengan kertas pasir supaya licin dan halus. Lepas itu, susun dan jalin buluh-buluh ini dengan akar pukang mengikut bentuk dan jenis serkap yang kita nak. Jika serkap Kedah, bukaan dan mulutnya bersaiz sederhana berbanding serkap Perlis dan serkap Banjar yang mempunyai saiz bukaan lebih luas. Akhir sekali, baru kita sapu varnis supaya nampak lebih berkilat dan kemas,” terang Pak Mael sambil tersenyum. Saya dan papa hanya mengangguk.
Sememangnya proses menghasilkan serkap rumit, tetapi papa bukanlah orang yang suka mengambil kesempatan. Dia hanya mahu menolong orang kampung memasarkan produk mereka. Selama ini, sudah banyak hasil pertukangan orang kampung yang terjual di kedai papa, termasuklah serkap-serkap yang dihasilkan oleh Pak Mael.
Kadangkala, penduduk kampung menghantar kerepek dan kuih tradisional ke kedai tanpa diminta, lantas papa menerimanya dengan tangan terbuka. Malah, papa membuat bayaran penuh kepada mereka, walaupun produk mereka belum tentu habis terjual.
Ada ketika, pelanggan datang dari ibu kota semata-mata untuk membeli serkap yang bervariasi di kedai papa untuk dibuat perhiasan. Apa tidaknya, ada beberapa jenis serkap yang berbeza dijual di sini sama ada serkap Perlis, serkap Kedah mahupun serkap Banjar. Kearifan seni tangan masyarakat Melayu dalam penghasilan kraf tangan memang tidak dapat dinafikan lagi. Maka, tidak hairanlah ramai orang mencari produk-produk kraf tangan yang dijual di kedai papa.
“Mei, apa kamu buat di luar? Malam sudah larut, tak baik duduk di luar,” tegur papa.
“Papa! Mei nak cakap sesuatu.”
“Tentang apa?”
Saya segera menghampiri papa dan merangkul tangannya. Segala bebanan di jiwa, saya ceritakan. Semua kisah yang tidak enak, saya sampaikan. Biar tiada satu pun terlepas daripada pengetahuan papa.
Wajah papa terus berubah tatkala mendengar khabar itu. Kerut di dahinya semakin jelas kelihatan. Suasana bungkam seketika. Bebola matanya bergerak ke kiri dan ke kanan. Kakinya melangkah menghampiri kerusi malas, lalu pinggulnya dilabuhkan ke atas kerusi itu. Perlahan-lahan papa mengukir senyum.
“Datuk kamu pernah bercerita. Lebih 80 tahun lepas, atau lebih tepat bulan Disember 1941, ketika Jepun mendarat di Tanah Melayu, keadaan menjadi huru-hara. Hanya dalam beberapa hari Jepun berjaya menawan Jitra dan Alor Setar. Ramai orang menjadi mangsa keganasan mereka. Orang Cina paling teruk menerima kesan kerana dipengaruhi sentimen Perang China-Jepun.”
“Jadi, apa kaitannya?” soal saya, keliru.
“Jadi, penduduk yang takut akan kekejaman Jepun bertindak melarikan diri daripada kawasan pekan. Mereka termasuklah datuk kamu, Pak Mael, bapa Halim dan beberapa orang kampung yang lain. Mereka kemudiannya telah membuka petempatan di sini dan menamakannya Kampung Muhibah. Tempat papa dan kamu dibesarkan,” papa memandang tepat ke mata saya. Saya mengangguk.
Jelas papa lagi, muhibah bermaksud kasih mesra, perasaan persahabatan dan kemesraan. Maka, kawasan ini dinamakan Kampung Muhibah sempena semangat setia kawan antara masyarakat pelbagai kaum. Biarpun berbeza budaya dan agama tetapi mereka saling menjaga dan melindungi antara satu sama lain. Sekalipun penjajah dan pengganas silih berganti menunjukkan kuasa, masyarakat kampung ini kekal menyimpan rahsia demi kebaikan seluruh isi masyarakatnya.
“Sudah lebih lapan dekad keluarga kita duduk di kampung ini, tetapi tidak pernah sekalipun papa rasa dipinggirkan. Kita bernafas dengan udara yang sama, melihat langit yang sama, hidup dalam persekitaran yang sama tanpa ada prejudis. Lantas, apakah yang menyebabkan kamu berfikiran negatif?” soal papa.
Saya terdiam. Kata-kata papa ada asasnya.
Sudah lama keluarga kami berasimilasi dengan budaya hidup masyarakat Melayu di sini. Makanan kami sama seperti mereka. Pakaian kami juga tidak jauh bezanya. Hanya kepercayaan dan status bangsa membezakan kami. Masyarakat di desa ini hidup sandar-menyandar umpama aur dengan tebing. Jika ada mana-mana keluarga yang ditimpa musibah, pasti satu kampung akan hadir membantu.
Papa juga sering membantu masyarakat di sini. Pernah surau di hujung kampung dilanda ribut menyebabkan kerosakan yang serius. Maka papa tanpa rasa terbeban menghulurkan bantuan wang ringgit untuk membaiki bahagian yang rosak. Bahkan, papa sendiri turun padang membantu penduduk kampung meski ada cakap-cakap belakang yang kurang enak didengar.
Layanan penduduk kampung kepada kami juga baik. Asalkan ada saja kenduri, pasti kami diundang sama untuk memeriahkan majlis. Jika ada rezeki lebih, pasti mereka akan berkongsi bersama-sama.
Masih jelas di ingatan saya peristiwa minggu lalu. Ketika saya dan papa berjalan-jalan di hujung kampung, kami berhenti seketika melihat traktor membajak sawah. Kelihatan sekumpulan remaja sedang mengekori rapat di belakang jentera itu bagi menangkap ikan. Pada arah berbeza, kelihatan beberapa orang dewasa sedang merejam serkap ke dalam air berulang kali. Saya melihat ada kocakan di dalam salah satu serkap yang direjam, pastinya ada ikan yang terperangkap dalam serkap tersebut.
“Heng, bawa anak bersiar-siarkah?” tegur Pak Mael dari penjuru sawah.
“Biasalah. Macam mana hasil padi tahun ini? Mesti dapat durian runtuh,” soal papa kepada Pak Mael.
“Durian runtuh? Mungkin tidak kali ini, Heng. Kau lihatlah sendiri. Hampir separuh relong padi aku rosak. Semuanya rebah ke bumi dek serangan tikus. Seminggu selepas serangan, baru aku sedar pokok padi bertukar coklat dan reput, padi bunting dimakan tikus. Petak sawah di seberang sungai sana juga ada masalah. Habis pokok-pokok padi tumbang dek serangan hawar seludang,” jelas Pak Mael panjang lebar.
Setahu saya, Penyakit Hawar Seludang berpunca daripada serangan kulat Rhizoctonia Solani yang kebiasaannya menyerang pada peringkat padi beranak maksimum. Kemudiannya, akan menyebabkan padi hampa terutama pada bahagian tangkai. Walau bagaimanapun, penyakit ini boleh dielakkan jika dikawal dengan baja dan racun yang bersesuaian.
“Sabarlah Pak Mael. Barangkali bukan rezeki Pak Mael musim ini. Musim depan mungkin dapat rezeki melimpah ruah,” pujuk papa.
“Iyalah, sudah lumrah kami sebagai petani. Mujurlah kau sanggup beli dan jual semula serkap-serkap aku itu. Setidaknya, aku dapat tambah pendapatan. Haa, ini rezeki kau. Nah, ambillah ikan-ikan ini!” pelawa Pak Mael sambil tangannya menggagau ke dalam mulut raga batang miliknya.
Kelihatan ikan haruan, keli, puyu dan sepat dikeluarkan seekor demi seekor daripada raga ikan, kemudian dimasukkan ke dalam plastik. Lalu, bungkusan plastik itu diserahkan kepada papa. Papa mengucapkan rasa syukur atas pemberian itu. Kami menyambung perjalanan ke rumah.
Saya tidak mampu menafikan kebaikan orang kampung kepada keluarga saya. Cuma, hal yang menjadi kegusaran hati saya ialah sikap Halim sahaja. Barannya, ibarat bom jangka, bila-bila masa sahaja boleh meletus. Saya khuatir jika dia ada menyimpan dendam terhadap papa. Apatah lagi, ini buka kali pertama Halim membangkit isu ketidakpuasan hatinya terhadap papa.
“Kalau Halim menghasut Pak Mael dan orang kampung untuk membenci papa bagaimana?” saya melontarkan rasa gusar di dada.
“Kamu sendiri tahu sikapnya. Bukan papa seorang yang menjadi bahan amarah hatinya. Peribahasa Cina ada menyebut, ada bukit mesti ada air, ada orang mesti ada hantu. Sudahlah! Usah bebankan fikiran kamu dengan hal yang tidak sepatutnya,” papa bingkas daripada tempat duduk. Saya ditinggalkan dengan seribu satu persoalan.
***
Pohon siantan batangnya erang,
bunga cempaka dijadikan pati;
Ibarat menggunakan serkap jarang,
kesahihan cerita belum terbukti.
Rachan melemparkan senyuman sinis tatkala dia membaca serangkap pantun di hadapan bilik kuliah. Subjek Penulisan Kreatif pada semester ini menuntut saya dan rakan-rakan kuliah menghasilkan pelbagai genre karya kreatif. Kata pensyarah, kami harus berupaya memahami dan menaakul setiap karya, baik yang tersurat mahupun tersirat.
“Kamu menyindir saya?”
“Untuk apa saya menyindir kamu?” Rachan ketawa kecil.
Dia memang gemar mengusik saya sejak di bangku sekolah lagi. Kami bertuah kerana dapat belajar di universiti yang sama. Paling tidak, senang saya meminta bantuannya jika ada urusan melibatkan kampung.
“Hanya kamu yang tahu kisah saya di kampung. Menyesal saya ceritakan kepada kamu!”
“Saya hanya membina pantun tadi secara spontan apabila pensyarah minta. Itu saja. Janganlah serius,” jelas jejaka berketurunan siam itu. Saya mencebik manja.
Pantun sememangnya puisi tradisional yang istimewa. Jalinan baris pembayang dan maksud dalam serangkap pantun mampu membawa seribu satu makna tersirat. Saya benar-benar kagum dengan kebijaksanaan masyarakat terdahulu menjalinkan nilai estetika dan akal budi dalam seni berbahasa. Atas alasan itulah, saya mengambil jurusan pengajian berkaitan bahasa Melayu.
Kring! Kring!
Telefon bimbit Rachan berbunyi. Dia segera mengangkat. Perbualan kami tergantung seketika.
“Mei, saya dapat panggilan dari kampung. Tok Imam dan orang kampung sudah cuba hubungi kamu, tetapi panggilan tidak diangkat. Katanya…”
“Kenapakah? Macam penting sahaja!”
“Rumah kamu terbakar!”
Mata saya terbelalak mendengar kata-katanya. Lutut terasa longgar. Tubuh menggeletar. Jiwa saya seolah-olah terbang dari jasad yang tidak bermaya. Saya kehilangan kata. Minda juga tidak tahu mahu melakukan apa? Mujur, Rachan menawarkan diri menghantar saya ke kampung.
“Papa kamu sudah jawab panggilan?” soal Rachan.
Saya menggeleng kepala. Sudah berkali-kali saya cuba menghubungi papa, tetapi tetap tidak diangkat. Seribu satu kemungkinan berlegar-legar di minda. Ketakutan yang selama ini bersarang di jiwa, kini menjadi nyata!
Saya tidak mampu membayangkan jika perkara buruk berlaku kepada papa. Harta benda jika musnah boleh ditukar ganti, tetapi sosok yang bergelar papa tidak mungkin dapat dicari. Sejak ibu meninggal dunia, hanya papa tempat saya bermanja, menyemai kasih dan berkongsi segala rasa. Mana mungkin saya dapat bertahan hidup jika papa juga tiada! Saya hanya mampu berdoa agar Tuhan melindungi papa.
“Ini mesti kerja Halim!” Saya menebak.
Rachan tidak memberi sebarang reaksi.
Satu demi satu insiden yang melibatkan Halim berlegar-legar di dalam kotak ingatan. Papa pernah bercerita tentang kejadian yang terjadi di surau. Halim tanpa rasa bersalah menjatuhkan air muka papa di hadapan warga kampung.
Halim menuduh papa ada udang di sebalik batu kerana membantu membaiki kerosakan di surau. Mujurlah, Tok Imam dan warga kampung yang lain segera menyanggah tuduhannya. Apatah lagi, papa memang terkenal dengan sikapnya yang ringan tulang dan kaya hati.
Bukankah semua agama menganjurkan umatnya supaya berbuat baik kepada makhluk dan menjauhi kerosakan serta perbuatan jahat? Jadi, tidak salah jika papa membantu masyarakat yang ditimpa musibah.
Halim juga pernah bertindak merosakkan arca yang dibina sempena sambutan bulan kemerdekaan dek berbeza pendapat dengan orang lain. Sikapnya itu seperti tidak berpucuk di atas enau. Padanya, pendapat orang lain tidak ubah seperti debu di pinggir jalan. Maka, tidak mustahil dia sudah berani untuk bertindak melampaui batas.
“Kemarahan hanya akan menyebabkan kamu kehilangan kewarasan. Orang yang berada dalam keadaan marah itu, ada ketika dia menjadi tuan, ada ketika dia menjadi Tuhan,” bicara Rachan memecahkan kesunyian.
“Apa maksud kamu?” saya memandang Rachan dengan rasa ingin tahu.
“Bahasa tubuh kamu cukup menggambarkan api kemarahan yang membakar jiwa. Manusia yang berada dalam keadaan marah lidahnya akan menutur kata sesuka hati, mengarahkan orang lain mengikut kehendaknya. Ketika itu, dia menjadi tuan. Apabila dia melampau batas, maka dia akan membuat bermacam andaian. Malah, dia tegar menentukan hukuman seolah-olah dialah Tuhan. Soalnya, layakkah kita sebagai manusia mengambil kerja Tuhan?” penjelasan Rachan membuat saya tersentak.
Saya merapatkan tubuh ke penyandar kerusi kereta. Jari-jari yang tergenggam, saya luruskan. Pandangan dilemparkan ke arah luar tingkap. Saya cuba menenangkan diri seadanya.
“Amarah tidak mungkin dapat menyelesaikan masalah, justeru akan menimbulkan satu demi satu lagi masalah baharu,” tambah Rachan lagi.
Kata-katanya benar. Saya tidak seharusnya membiarkan emosi menghanyutkan akal sihat. Lebih baik saya menangis daripada marah. Setidaknya, saya tidak menyakiti hati orang lain. Sementara, air mata yang mengalir pasti dapat menginsafi kekhilafan diri. Biarpun apa sahaja yang terjadi, saya harus berdamai dengan takdir.
Kereta Rachan meluncur memasuki perkarangan rumah saya. Saya memerhati segenap penjuru, mencari cinta hati yang dikasihi. Syukur, papa berdiri tepat di depan laman rumah. Seusai kereta berhenti, saya segera membuka pintu dan berlari mendapatkan papa. Tubuhnya, saya peluk erat. Air mata mengalir laju membasahi pipi. Tiada nikmat yang dapat saya dustakan saat ini. Melihat tubuh papa masih teguh berdiri sudah memadai bagi diri ini.
Jelas papa, kebakaran terjadi akibat kelalaiannya sendiri semasa membakar sampah hingga api marak dan membakar bahagian belakang rumah. Mujurlah Halim dan rakannya betindak pantas membantu memadamkan api. Jika tidak, pasti seluruh rumah hangus terbakar.
Ah, saya terperangkap dengan prasangka sendiri! Terkadang kebenaran memang sukar dicerna oleh minda. Namun, kita harus menerimanya kerana hal itu lebih baik berbanding hidup dalam ilusi ciptaan sendiri. Saya harus segera bertemu dengan Halim. Orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa.