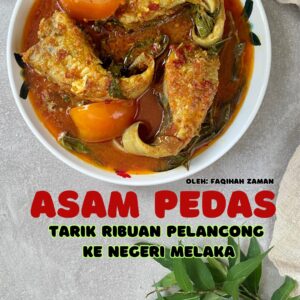RAHIMA terjaga apabila suaminya batuk tidak putus-putus. Dia segera menepuk perlahan belakang suaminya dengan harapan batuk itu akan reda.
“Ima ambilkan air, ya?” Rahima menghulurkan kakinya untuk turun dari katil namun lengannya ditahan. “Ada apa-apa lagi yang abang nak saya ambilkan?” sambung Rahima.
Hisyam menggeleng namun pandangannya berkaca.
Hati isterinya dipagut risau.
“Abang, kita pergi ke hospital, ya?”
Namun pujukannya sekadar dibalas dengan gelengan.
“Esok saja kita pergi. Isteri abang ni bukannya biasa memandu malam. Lagipun, abang rasa badan ni letih sangat.” Hisyam mengusap bahu isterinya, cuba meyakinkan wanita yang mulai runsing itu.
Dengan berat hati, Rahima mengangguk. “Ima ke dapur ambilkan abang air,” katanya perlahan.
“Abang minta maaf kerana susahkan Ima.” Bicara Hisyam menjentik sendu di tangkai hatinya.
Sambil menggeleng, Rahima segera ke dapur. Perasaannya diruntun hiba. Segelas air suam dituang ke gelas kaca, kemudian dia kembali ke bilik. Semasa menaiki tangga, kedengaran lagi batuk-batuk yang berlarutan. Langkahnya dipercepat. Pintu bilik ditolak pantas. Suaminya tidak kelihatan di birai katil. Hatinya lega apabila mendengar bunyi air dari bilik mandi. Rahima menuju ke pintu bilik mandi, dan menunggu.
Batuk suaminya kedengaran lagi. Berselang-seli dengan dengus nafas termengah-mengah.
“Abang,” panggil Rahima sambil mengetuk pintu.
Tangannya memulas tombol pintu. Tidak berkunci. Pintu ditolak. Hisyam sedang berkumur-kumur di singki. Wajahnya pucat.
“Abang yang risau dengan wajah Ima yang panik macam tu. Abang tak apa-apa. Akhir-akhir ni, cuaca tak menentu.” Hisyam mengukir senyum.
Setelah mengeringkan wajahnya dengan tuala putih di tepi singki, tangan isterinya dipimpin keluar dari bilik mandi itu.
“Ima boleh memandu malam. Abang jangan nak tahan-tahan sakit tu. Beritahu Ima jika abang nak ke hospital malam ini, ya?” Rahima meminta kepastian.
“Anak-anak kita yang sedang lena tu siapa boleh tengok-tengokkan kalau kita ke hospital malam ni? Kasihan kalau dikejutkan sekali tetapi jika dibiarkan di rumah pula, abang tak sanggup. Orang jahat boleh muncul bila-bila masa. Esok sahaja kita ke hospital.” Hisyam menenangkan isterinya.
Rahima mengangguk. Betul kata suaminya. Tidak ada sesiapa yang boleh menengok anak-anak pula nanti.
“Abang minum air suam ni sekarang. Kalau dah sejuk, risau abang batuk-batuk lagi,” pesannya.
Hisyam mengangguk.
Apabila isterinya membelakangi, dia segera menanggalkan kemeja-T yang terkena percikan darah semasa dia batuk di dalam bilik mandi tadi. Dia tidak mahu bintik-bintik merah itu menambah gundah di hati isteri yang amat dicintainya itu. Baju itu segera dimasukkannya ke dalam bakul kain kotor di belakang pintu.
Hisyam duduk di birai katil. Gelas berisi air suam dicapai. Air suam yang melalui tekak terasa amat melegakan. Dia menarik nafas panjang, memastikan oksigen menyentuh rongga dada sebelum dilepas semula.
“Ima, tidurlah. Esok anak-anak nak ke sekolah. Kejutkan abang kalau abang tak terjaga. Abang suka melihat anak-anak kita bersiap dengan pakaian seragam mereka. Tambah lagi dengan beg berisi buku tersangkut di bahu. Abang sentiasa mendoakan kesejahteraan anak-anak kita di dunia dan di akhirat,” bicaranya diiringi senyum di bibir.
“Abang usah risau. Hakim pun dah masuk tingkatan tiga, Lukman dah tingkatan satu dan Arif pula tahun enam.” Rahima ikut tersenyum di samping Hisyam.
“Abang tak risau sebab Ima akan dijaga oleh tiga orang pengawal peribadi paling setia suatu hari nanti. Ima jangan buat kerja yang berat-berat. Kalau paip rosak, panggil Hakim. Kalau pintu rosak, panggil Lukman. Kalau pagar rosak, panggil Arif,” usik Hisyam, bergurau.
“Kan Ima ada empat orang pengawal peribadi termasuk abang. Kenapa tak senaraikan abang sekali?” soal Rahima.
Hisyam menatap wajah isterinya sesaat kemudian berkata, “Abang dah sering sakit-sakit. Risau tak cukup kuat nak melindungi Ima nanti. Biarlah anak-anak kita yang mengambil alih tugas sebagai pengawal peribadi ibu mereka.” Hisyam menyambung harapannya.
Rahima mengangguk mengiakan. Tangan suaminya dikucup lama. Berkoyan-koyan kata sedang membuak ingin diluahkan namun seperti ada sesuatu yang menghalang. Dadanya terasa sebu dan bibirnya terasa berat.
‘Ima cinta dan sayangkan abang sangat-sangat,’ ucapnya. Namun ucapan itu hanya bergema dalam dada, tidak terungkap.
“Ima tak apa-apa? Kenapa tenung abang macam tu?”
Rahima tersentak. Fikirannya melayang seketika. Dia segera menggeleng. “Ima doakan semoga abang cepat sihat,” bisiknya spontan, menjawab persoalan Hisyam.
“Abang rasa kelopak mata ni dah berat sangat. Kita tidur, ya?”
Rahima mengangguk sambil memejamkan mata apabila kucupan sayang hinggap sesaat di dahinya. Kucupan yang lazim diterimanya setiap kali sebelum tidur.
Rahima terjaga apabila terdengar bunyi batuk yang kuat dan berlarutan. Dia meraba ke tepi dan mendapati tempat tidur suaminya kosong. Dia segera bangun dan menajamkan mata mengamati sekeliling. Lampu dari kamar mandi sedang menyala. Rahima segera menuju ke sana.
Nasib baik pintu tidak dikunci dari dalam. Sebaik daun pintu ditolak, Rahima tergamam. Hisyam sedang duduk menyandar dengan cecair merah meleleh dari bibirnya. Titisan-titisan merah juga kelihatan di tepi singki.
“Abang!”
Tubuh suaminya yang separuh lembap dipeluk. Dia cuba membawa tubuh itu berdiri namun kudratnya tidak mampu.
“Abang boleh bangun sendiri.” Terketar-ketar suara Hisyam.
“Ima kejutkan Hakim, ya? Abang tunggu sekejap.”
Rahima hendak beredar namun lengannya ditarik. Dilihatnya Hisyam menggeleng sambil berusaha untuk bangun. Rahima tidak mampu menahan air mata yang sudah bertakung. Dengan esak, dengan sepenuh kudrat yang ada, dia membantu suaminya agar boleh berdiri.
Tangan suaminya dibawa ke bahu dan perlahan-lahan memimpinnya keluar dari bilik mandi. Pakaian suaminya yang lembap segera ditukar dengan pakaian kering.
“Abang, kita ke hospital malam ni. Abang usah nak berdalih dan bertangguh lagi.” Suara Rahima kedengaran tegas.
“Anak-anak macam mana?”
“Sekarang dah pukul empat pagi. Sekejap lagi dah nak siang. Kita berdoa semoga tidak ada apa-apa yang buruk berlaku sepanjang kita ke hospital nanti. Selepas kemaskan keperluan, Ima kejutkan Hakim dan tinggalkan pesan.”
Sambil berkata, tangannya pantas menarik pakaian dan keperluan suaminya lalu dimasukkan ke dalam beg. Dompet suaminya turut dimasukkannya ke dalam beg yang sama. Risau jika kad pengenalan suaminya tertinggal, susah pula hendak berurusan nanti.
Hisyam tidak mampu berdalih lagi. Wajah isterinya yang tegang itu ditatap dengan penuh rasa bersalah. Dia menahan nafas berat dan cuba melepaskannya perlahan-lahan. Dia tidak sanggup melihat isterinya bertambah risau jika terdengar dengus nafas yang berbaur resah.
“Ima pergi ke bilik Hakim sekejap.”
Rahima keluar dari bilik dan sebentar kemudian dia sudah kembali.
“Mari, Ima pimpin abang,” katanya.
Hisyam menggeleng. “Abang rasa dah sihat sikit ni. Abang boleh berjalan sendiri. Mari, abang bawa beg tu,” pintanya sambil menghulur tangan.
“Tak apa, bang. Dalam beg ni pun hanya ada sepasang pakaian. Mari Ima pegang tangan abang.” Rahima menghampiri Hisyam.
“Isteri abang ni ada masanya degil tak dengar kata. Abang rasa nak tarik-tarik hidung tu. Apa boleh buat. Sekarang ni, abang tak sihat. Tunggulah nanti.” Hisyam sempat bergurau.
Rahima hanya senyum kecil.
Di luar bilik, Hakim sedang menanti. Selepas ibunya meninggalkan pesanan tadi, Hakim tidak mampu melelapkan mata. Dia terus bangun dan menunggu ayahnya di luar pintu.
“Eh, Hakim. Kenapa tak tidur?” Hisyam memeluk lalu mengucup dahi anak sulungnya itu.
“Tak ada apa-apa, ayah. Hakim nak tengok ayah saja.” Hakim membalas pelukan ayahnya, erat.
“Sebaik saja selesai pemeriksaan di hospital, ibu dan ayah akan segera pulang. Nanti ayah hubungi Pak Cik Hassan, minta dia hantar kamu semua ke sekolah, ya? Hakim pandai siapkan adik-adik nanti?”
Hakim mengangguk. Dia menghantar ibu dan ayahnya hingga ke muka pintu. Hatinya sayu melihat mereka masuk ke dalam perut kereta dan kereta itu mula bergerak pergi.
Cuaca sejuk subuh itu membuatkan batuk Hisyam semakin menjadi-jadi. Dalam perjalanan ke hospital, beberapa kali dia terbatuk kuat dan disertai darah. Rahima hampir tidak dapat menumpukan perhatian pada pemanduannya kerana berulang kali menoleh, melihat keadaan suami di sebelah.
“Ima tengok saja depan tu. Abang tak apa-apa. Kalau kita kemalangan, anak-anak akan kehilangan kita berdua,” Hisyam berkata dengan termengah-mengah di celah batuknya.
Rahima menggigit bibir, cuba menahan air matanya agar tidak jatuh namun air yang suam-suam masin itu mengalir juga. Berkali-kali dia memejam celik matanya kerana agak kabur digenangi air mata. Hospital yang dituju dirasakannya teramat jauh.
Tempat letak kereta lengang sahaja sewaktu mereka tiba di perkarangan hospital. Rahima terus meletakkan keretanya di kawasan yang paling hampir dengan pintu kecemasan.
“Abang, Ima panggil staf dalam tu dulu. Sekejap saja, ya?”
Hisyam mengangguk sambil matanya tidak lepas memandang air mata yang berguguran membasahi wajah isteri tercinta. Perasaan bersalah yang menghentam jiwanya, hanya Dia sahaja yang tahu.
Sebentar kemudian, Rahima muncul semula bersama dua orang pembantu bilik kecemasan yang membawa usungan dan seorang doktor. Pintu di sebelah penumpang dibuka dan Hisyam dialihkan ke atas usungan dengan pantas namun penuh hati-hati. Doktor menyuluh wajah Hisyam dengan lampu suluh kecil untuk melihat keadaan pesakit itu kemudian segera dibawa masuk ke bilik kecemasan.
Hisyam dibaringkan ke atas katil. Beberapa orang jururawat dan doktor tadi terus mengerumuninya. Rahima diminta menunggu di hadapan kaunter dan akan diberitahu jika perlu.
“Doktor, boleh saya bercakap dengan suami saya? Saya janji sekejap saja,” pinta Rahima separuh merayu.
“Boleh tapi tolong ya, puan. Seminit saja. Kami perlu segera periksa keadaan pesakit,” balas doktor itu.
Rahima mengangguk kemudian langkahnya pantas menghampiri katil suaminya. Tubuh suaminya dipeluk erat beberapa saat. Pipinya semakin basah.
“Abang harus bertahan, ya? Ima tunggu abang di luar. Ima tak pergi mana-mana. Kalau abang perlukan Ima, abang suruh doktor atau jururawat tu panggilkan Ima, ya?”
Hisyam mengangguk lemah. Wajah isteri tercinta ditatap sepuasnya. Dia dapat merasakan degupan jantungnya amat lemah. Wajah anak-anak muncul dengan jelas seorang demi seorang. Dia mahu meninggalkan pesan tetapi dia tidak mempunyai kudrat yang cukup untuk meluahkan kata-kata. Rahima menggenggam tangan Hisyam yang dingin. Bibir pucat itu bergerak-gerak seperti ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak ada suara yang muncul.
“Puan, sila tunggu di luar, ya? Kami mahu menjalankan pemeriksaan segera,” kata seorang jururawat.
Rahima mengangguk dengan berat. Mata Hisyam yang sayu mengunci pandangannya saat kakinya mengundur perlahan-lahan meninggalkan ruangan yang dingin itu.
Rahima duduk di salah sebuah kerusi plastik di hadapan kaunter. Suasana amat dingin dan sunyi. Tidak ada seorang pun di ruangan itu kecuali dua orang jururawat yang sedang duduk di dalam ruang bertutup kaunter pendaftaran. Rahima memeluk tubuh sambil mengetap bibir. Fikirannya sekejap memikirkan keadaan anak-anak yang ditinggalkan di rumah dan kembali semula kepada suami yang sedang diperiksa. Tanpa sedar, Rahima terlelap sambil menyandar di kerusi dengan kepala terlentok ke dinding simen.
“Puan.” Satu suara mengejutkannya.
Segera Rahima mencelikkan mata dan seorang jururawat sedang berdiri di hadapannya.
“Banyakkan bersabar,” sambung jururawat itu.
Rahima hampir ternganga, matanya membulat dengan dahi berkerut menunggu ayat yang seterusnya.
“Puan boleh duduk di sebelah suami puan dan hubungi keluarga terdekat. Mungkin kehadiran mereka boleh menambah semangat suami puan. Dia agak tenat,” tambah jururawat itu sebelum berlalu.
Buat seketika, Rahima terkaku.
Hubungi keluarga terdekat? Agak tenat?
Dengan tangan terketar-ketar, Rahima mengambil telefon bimbit dari dalam beg dan mencari nombor-nombor yang berkenaan.
Ayah dan ibu serta adik-beradik sebelah suami segera dihubungi. Begitu juga keluarga terdekatnya. Sebaik mendengar berita tersebut, masing-masing berusaha untuk datang secepat mungkin. Rahima baru hendak mendail nombor rumah tetapi jarinya tiba-tiba terhenti.
Dia tidak dapat membayangkan bagaimana Hakim akan mengawal keadaan jika adik-adiknya risau apabila mengetahui keadaan ayah mereka. Maka, Rahima mengambil keputusan untuk tidak memberitahu Hakim buat waktu ini.
Selepas menghubungi semua keluarga yang dirasakannya perlu, Rahima segera masuk ke dalam ruang yang menempatkan katil-katil pesakit. Hisyam sedang terlantar, berselimut putih menutupi hampir ke lehernya. Mata itu terpejam rapat dan dia sedang diberikan bantuan pernafasan oksigen. Mesin ECG sedang aktif di sebelah katil.
Rahima duduk. Tangan suaminya dicapai dan jari jemari dingin itu digenggam erat lalu dikucup satu per satu. Air matanya tumpah lagi. Dia teresak-esak. Wajah pucat dan dingin itu ditatap puas-puas.
Seorang doktor muncul dan berdiri di sebelahnya. “Puan bercakaplah. Walaupun sedang terbaring begitu, dia boleh mendengar. Mudah-mudahan semangatnya kuat melawan kesakitan,” kata doktor tersebut.
Rahima berpaling menghadap doktor itu lalu bertanya. “Bagaimana keadaan suami saya yang sebenarnya, doktor? Dia sakit apa?”
“Dia mengalami jangkitan kuman pada paru-paru. Kuman itu sangat aktif dan hampir merebak ke organ-organ penting yang lain,” jawab doktor.
“Dia akan sembuh, kan?”
“Ya, dia akan sembuh. Kami sedaya upaya akan bantu,” jawab doktor itu dan kemudian beredar.
Selang setiap lima belas minit, doktor akan datang memeriksa keadaan Hisyam, memberi suntikan, dan menukar botol air yang tergantung di tepi katil dan bersambung ke lengan. Rahima memerhatikan segala-galanya.
Tepat jam tujuh pagi, debaran Rahima memuncak apabila dua orang doktor dan tiga orang jururawat berkejar ke katil Hisyam. Rahima diminta menunggu di kawasan kaunter luar lalu tabir di sekeliling katil dirapatkan. Rahima menangis sambil berjalan ke hulu ke hilir di sekitar katil yang bertutup rapat dengan tabir itu. Dia tidak keluar ke ruang menunggu seperti yang diarahkan. Dia tidak mahu pergi jauh.
“Puan!”
Rahima segera menerpa ke arah doktor yang memanggilnya.
“Pergilah teman suami puan. Dia sangat lemah dan jika ditakdirkan, dia akan pergi bila-bila masa. Jantungnya terlalu lemah. Kami tidak boleh menjalankan pembedahan.”
Kata-kata itu umpama halilintar yang membelah jantungnya. Dia hampir tidak percaya dengan pendengarannya sendiri dan sekiranya boleh, dia tidak mahu percaya akan kata-kata doktor itu.
Rahima menyingkap tabir hijau yang mengelilingi katil. Langkahnya terasa berat dan hampir tidak mampu berjalan. Perasaannya seolah-olah hilang ditelan ke alam lain. Dia tidak sedar punggungnya sudah berlabuh di atas kerusi di sebelah tubuh dingin yang terlantar itu.
Rahima menatap monitor yang menunjukkan garisan-garisan yang tidak dia mengerti maksudnya. Dalam drama atau filem, jika garisan itu semakin mendatar, pesakit semakin tenat. Jika garisan itu terhenti, bermakna tamatlah riwayat pesakit tersebut.
Rahima melarikan matanya daripada menatap garisan-garisan yang terpapar. Dia tidak sanggup. Wajah suaminya yang seolah-olah tidur diusap perlahan. Dingin!
“Abang, kenapa semalam amat payah Ima ucapkan cinta dan sayang Ima pada abang? Kenapa pada saat abang mungkin sudah tidak mampu mendengar, barulah lidah ini mudah mengucapkan cinta dan sayang? Andai saja Ima tahu yang abang akan begini, Ima akan mengucapkan kata-kata itu setiap waktu.” Rahima memeluk lengan suaminya erat. Dia tunduk, menangis dan menangis.
Ketika Rahima mengangkat kepala, pandangannya tanpa dipinta tersinggah pada garisan-garisan yang semakin halus di wajah monitor. Jantungnya hampir berhenti apabila melihat garisan itu tidak ada turun naiknya lagi. Garisan itu hanya mendatar. Mendatar dan semakin perlahan. Degup jantungnya seolah-olah ikut terhenti saat garisan mendatar itu mula menjadi garisan putus-putus dan akhirnya …
Rahima tahu, saat itu nadi suaminya telah terhenti!
“Doktor!”
Jeritannya mengundang doktor dan jururawat yang berhampiran. Dia diminta meninggalkan katil. Rahima berundur sedikit dan dirasakannya dunia tiba-tiba semakin sempit dan segala benda di sekelilingnya seperti menghimpit. Nafasnya sesak dan pandangannya menjadi kelam. Akhirnya, dia tidak sedar akan apa-apa lagi.
*****
“Ima, takziah,” bisik satu suara di tepi telinga.
Rahima membuka mata perlahan-lahan. Cahaya yang menjamah mata amat menyilaukan. Pedih menghiris.
“Ima nak berehat di rumah atau ikut sekali ke pusara arwah?” Ibunya bertanya.
Lama Rahima diam. Wajah suami tercinta terbayang di ruang mata. dia tidak sanggup melihat jasad yang dibelai selama ini diturunkan ke liang lahad. Ditimbus.
“Tak mengapa. Biarlah Ima di rumah. Esok Ima akan melawat pusara arwah bersama anak-anak Ima,” putusnya.
Ibu mengangguk. Faham akan nestapa yang sedang ditanggung.
“Abang Hisyam, insan sebaik abang dijemput terlalu awal. Walau hakikatnya, tidak ada istilah awal atau lambat andai sudah tiba masa kita dijemput pulang. Namun Ima tetap merasakan yang abang terlalu awal untuk pergi. Ampunkan hamba-Mu ini, Ya Allah. Terima kasih kerana meminjamkan insan baik itu sebagai suamiku di dunia yang sementara dan pertemukanlah kami berdua di akhirat nanti. Aku mahu menjadi bidadarinya di sana.”
Rahima memejamkan mata. Membiarkan air mata mengalir. Semoga kesedihannya ikut luruh bersama air mata itu. Hanya nadinya yang terhenti. Cinta dan kasihnya tidak pernah mati.