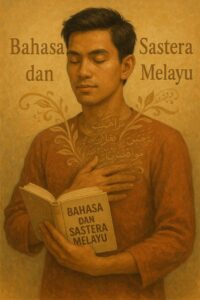‘DI PENTAS gemilang itu, apakah yang sebenarnya dinilai, rupa atau jiwa?’
Aku duduk di barisan belakang. Tepukan gemuruh seolah-olah ingin meruntuhkan bangunan Kadazan Dusun Cultural Association (KDCA) itu. Aku duduk dengan tenang mencatat setiap langkah, senyuman dan melihat gaun yang berkilau.
Saat asyik menyaksikan pertandingan Unduk Ngadau, benakku disapa kenangan tentang satu nama lama yang kerap hadir dalam bisikan perlahan, seakan enggan dilupa, Huminodun. Legenda yang cukup sebati dengan masyarakat Sabah. Seorang anak perempuan daripada Kinoingan dan Sumundu. Cantik, berhati mulia dan rela berkorban demi membantu masyarakatnya menyebabkan munculnya pertandingan Unduk Ngadau yang menjadi rujukan atas semangat Runduk Tadau. Runduk Tadau dalam bahasa Kadazandusun bermaksud gadis yang dimahkotakan sinaran cahaya matahari. Huminodun, Unduk Ngadau, bukan sekadar menjadi ratu, tetapi lambang pengorbanan.
Namun kini, persoalannya, ‘adakah kita masih menobatkan semangat atau hanya menata pesona diri?’ Hati kecilku berlagu sayu, seakan resah menagih jawapan yang kian kabur.
Daripada sepuluh orang peserta akhir Unduk Ngadau yang baru diumumkan oleh juruacara, masing-masing muncul di atas pentas Hongkod Koisaan, berjalan penuh yakin dengan busana tradisional dari belakang pentas. Mereka di hadapan penonton dengan senyuman yang manis, anggun dan menawan. Mataku tertuju kepada salah seorang peserta akhir, iaitu Carol. Dia yang pernah kutemui sebelum ini. Aku yang mengheretnya dalam perdebatan tentang makna sebenar Unduk Ngadau ketika itu.
“Unduk Ngadau?” Kata Carol, beberapa minggu lalu. Itu sebelum malam penobatan dua puluh peserta Unduk Ngadau daerah. Dua puluh orang itu akan disiapkan untuk berentap pada Malam Unduk Ngadau.
Ketika itu, aku sempat mencuri waktu untuk mewawancara Carol, di ruang rehat dewan KDCA. Ketika itu, Carol baru usai sesi latihan. Wajahnya manis, senyumannya tidak lekang di bibir, sesuai dengan piawai kecantikan Unduk Ngadau saat ini. Lekuk pipinya dalam, keningnya terangkat halus dan setiap gerak tubuhnya teratur sesuai dengan latihan ketat yang telah diikutinya. Namun, senyuman itu menjadi pudar apabila aku melontarkan satu pertanyaan ringkas kepadanya.
“Apa sebenarnya erti Unduk Ngadau bagi kamu?” Aku menyuarakan pertanyaan tanpa perantara, tanpa kata pembuka, menanti jawapan yang aku harap lahir dari hati.
“Unduk Ngadau?” Sebaris kerutan muncul di dahi Carol, mencerminkan kehairanan. Dia seolah-olah membuat persoalan sendiri sebelum melanjutkan jawapannya. “Bagi saya Unduk Ngadau hanya untuk menonjolkan piawai kecantikan seseorang perempuan. Siapa paling anggun, paling menyerlah maka dialah Unduk Ngadau bukan?”
Aku terdiam sebentar, tidak suka dengan nada suaranya, juga ligat memikirkan kesinambungan bagi semua itu. Jelas ketidakpuasan hati melanda jiwa dengan serta-merta. Namun, dengan spontan aku kembali bertanya kepadanya umpama peluru yang ditembak terus menerus, “Kamu tahu tentang Huminodun? Asal usul Unduk Ngadau atau tentang semangat dan pengorbanannya?”
“Ya, saya tahu cerita itu, bahkan saya masih kenal nama itu. Hanya legenda masyarakat Sabah yang menjadi pegangan orang tempatan. Tetapi itu cerita lama bukan?” Carol menjawab sambil tersenyum, namun kali ini senyuman itu semakin hambar. Tersirat ketidakselesaan, dia seolah-olah mahu menamatkan perbualan.
Aku menarik nafas panjang, memandang sekeliling kawasan rehat belakang pentas yang penuh dengan hiruk-pikuk. Bau minyak wangi menusuk hidung, kedengaran bunyi gelak tawa beberapa peserta lainnya berselang-seli dengan bunyi tapak kasut melangkah cepat di atas lantai yang tidak berjubin. Aku kembali menatap peserta itu, senyum sinis terukir di bibirnya.
“Jika Huminodun itu cerita lama, mengapakah masih ramai yang menganggap ia sebagai roh dan bayang sebenar kepada Unduk Ngadau?” Soalku memulakan kembali perbualan. “Bukankah warisan lama itu yang sepatutnya menjadi asas bukan sekadar rupa paras semata-mata?”
Carol mengangkat bahu, acuh tak acuh, kembali berhujah pantas, “Zaman sekarang sudah berubah, sekarang orang tetap mencari kecantikan, bukan cerita lama yang tidak relevan.”
Aku tersenyum kecil, “Jika hanya cantik tanpa roh dan bayang pengorbanan, apa beza Unduk Ngadau dengan peragaan fesyen? Busana tradisi yang diubah? Bukankah itu satu kehilangan makna yang besar?”
Carol menatapku dengan mata yang tajam, suaranya bergetar, seolah-olah menahan gelombang amarah yang hampir meluap, “Jika hendak ungkit cerita lama, kenalah faham zaman sekarang. Jika tidak suka, tidak perlu menontonnya, buang masa menjawab soalan-soalanmu ini!” Tempelak Carol.
Dengan langkah cepat, Carol berpaling dan berlalu, meninggalkan aku terpinga-pinga di situ. Aku tunduk, mencatat jawapannya tanpa balas. Tetapi dalam hati ada bara kecil yang menyala.
Lamunanku seketika terhenti, tersedar akibat tepukan dan sorakan para penyokong yang semakin bergema. Ada yang memakai pembesar suara memanggil nama peserta Unduk Ngadau yang disokong. Dari barisan belakang dewan yang semakin riuh, aku menyandarkan tubuhku di kerusi plastik merah. Di hadapan pentas, lampu berwarna-warni bersinar terang, disambut riuh oleh sorakan dan tepukan yang tidak pernah sepi.
“Hadirin sekalian, kita akan menyaksikan peragaan busana tradisi yang akan dipersembahkan oleh para peserta sebentar sahaja lagi!” Suara juruacara ternyata berjaya mendiamkan para penyokong yang hadir.
Diam itu hanya sementara. Penonton kembali bersorak apabila para peserta memperagakan busana tradisi. Di celah gema gong dan iringan muzik moden, satu demi satu busana muncul, bersulam kilauan moden, potongan yang disesuaikan mengikut rekaan terkini. Ada yang sarat dengan perhiasan seperti manik.
Aku menghembuskan nafas kesal. Sayangnya busana para peserta akhir Unduk Ngadau itu terlalu jauh dari tenunan halus hasil tangan nenek moyang dulu. Apakah ini yang kita wariskan? Rupa tanpa makna? Tradisi yang dibungkus cantik tetapi ternyata kosong dengan nilai budaya asal? Melihat banyaknya pakaian tradisi yang diperagakan, semuanya seolah-olah karya yang tidak bermakna.
‘Jika soal cantik sahaja, semuanya boleh jadi cantik. Tetapi sayang, cantik yang diperagakan sudah tiada maknanya lagi.’
Aku bergumam sendirian, memandang hiba ke arah pentas mencari makna di sebalik gemilang, bukan siapa yang tersenyum paling manis atau berjalan paling mantap dengan lenggoknya yang penuh gaya, tetapi siapa yang membawa warisan yang tulus.
Seperti melihat budaya yang sudah berada di ambang kehilangan. Hilang makna hilang semuanya, aku memejamkan mata sebentar, mencari ketenangan di balik suara riuh penonton.
‘Jika budaya sendiri dilupakan, entah apa makna mahkota yang bakal dipakai, jika tradisi sendiri ditinggalkan, entah apa makna membawa simbolik yang sudah tidak bernyawa,’ hatiku bising, otakku berputar bertanya, mencari jawapan yang masih lagi tersembunyi. ‘Huminodun … jika pengorbananmu ialah akar kepada segala yang indah dalam budaya ini, masihkah engkau dapat melihat semangatmu dalam lambaian moden kain ini?’
Aku terdiam.
Di atas pentas, fasa sudah memasuki penilaian terakhir. Sinar lampu menari di dinding, diiringi bunyi latar lagu yang bergema, suara penonton memuncak. Aku masih duduk di tempat yang sama, memerhati dari jauh. Di skrin besar, wajah sepuluh peserta akhir dipaparkan satu per satu.
Dan di situ … mataku terpaku kepadanya; wajah Carol. Wajah yang sama, tapi entah mengapa, aku berasakan kali ini matanya bersinar lain. Ada semacam kekuatan yang tidak terlihat tempoh hari.
Tibalah masa untuk sesi soal jawab, soalan akan diberi oleh juri kepada peserta, Carol membuat jantungku berhenti sebentar. Aku mengikuti. Aku menghayati. Suasana seketika hening, menunggu jawapan yang keluar dari mulut Carol.
“Apakah makna sebenar gelaran Unduk Ngadau bagi anda dan bagaimanakah anda melihat peranannya dalam masyarakat hari ini?” Suara juruacara garau, membacakan soalan.
Takdir umpama mempermainkan perasaanku, soalan yang pernah kulontar dengan penuh harapan kini kembali di hadapan ratusan mata yang memandang. Namun kini, soalan itu bukan lagi soalan yang dianggap remeh, namun menjadi nadi kepada jawapan yang lantang.
Mataku tidak lepas dari pentas itu, dengan penuh tanda tanya menatap wajah Carol. Di barisan belakang ini, aku bukan sesiapa, hanya pengkaji dan penonton kecil yang pernah bertanya dengan harapan dalam jiwa yang besar kepada Carol.
Soalan itu mirip soalanku kepadanya. Soalan yang ditolak mentah oleh Carol, kini dijadikan sebagai bendera perjuangan di medan perang, fakta logik dan sekadar jawapan.
Aku bertanya pada diriku sendiri. ‘Adakah dia sudah faham atau hanya sekadar bijak menyulam kata demi tepukan bergema dan kemenangan semata-mata?’
Carol menghela nafas dalam. Kemudian, dalam bahasa ibunda dia menjawab, “Bagi saya, Unduk Ngadau bukan sekadar pertandingan kecantikan wajah dan peragaan busana tradisi sahaja. Pertandingan ini merupakan peringatan terhadap pengorbanan Huminodun yang telah menyerahkan dirinya demi kelangsungan hidup bangsanya. Dalam dunia moden, saya sedar bahawa semangat itu harus ada. Bahkan …” sebelum meneruskan jawapannya dia berhenti seketika. Menghela nafas yang dalam membuat penonton semakin tertanya-tanya.
“Untuk menjadi pemenang yang dinobatkan sebagai Unduk Ngadau, wanita itu haruslah merangkumi semua aspek yang ada dalam diri Huminodun; tidak mementingkan diri sendiri, bersedia melayani komuniti dan menjadi inspirasi kepada semua perempuan dalam aspek kepintaran dan kemuliaan”.
Aku teruja sendiri. Bukan itu jawapan yang telah aku dengar tempoh hari.
Dengan penuh semangat Carol kembali meneruskan jawapannya, “Kita tidak sekadar perlu cantik pada luaran, namun harus membawa nilai perjuangan dan pengorbanan dalam diri kita. Seperti Huminodun. Ya. Seperti Huminodun.”
Dia mengakhiri jawapannya tepat dengan masa yang diberikan untuk menjawab oleh juri.
Penonton berdiri, sorakan semakin bergema. Aku pula terdiam. Lidahku kelu, akalku beku. Agak sukar untukku percaya, dengan jawapan seperti itu timbul persoalan dalam benakku. Adakah dia sudah betul-betul memahaminya? Kuharap dia yakin, serius dengan jawapannya. Mungkinkah kata-kataku dan segala soalanku tempoh hari telah menyatakan sesuatu dalam dirinya? Mungkinkah bara api dirinya yang tidak suka ditanya itu perlahan pudar? Atau mungkinkah diamnya selama ini ialah waktu yang dia perlukan untuk memahami, mencerna, dan akhirnya bersuara dengan makna yang lebih dalam?
Aku hanya diam, hatiku kubiarkan berbicara. Jika semangat Huminodun telah disedari oleh Carol, aku berharap itu bukan sekadar skrip. Bukan sekadar inginkan kemenangan, mahkota yang cantik dan piala yang besar. Namun, biarlah dia hidup dalam tindakan. Biarlah dia membenarkan kata-kata jawapan itu dalam catatan perjalanannya untuk menjadi Unduk Ngadau.
Kutarik nafas dalam-dalam, seolah-olah cuba menyedut bukan hanya udara, tetapi makna yang terselit dalam jawapan Carol sebentar tadi. Jawapan yang tak pernah kuduga lahir dari bibir manis yang sebelumnya enggan berbicara soal asal usul.
Ada sesuatu dalam tutur katanya yang meresap perlahan ke dasar jiwaku, membangkitkan harapan kecil bahawa semangat Huminodun belum sepenuhnya padam.
Aku menutup buku catatanku. Senyumanku mekar. Aku tidak tahu sama ada Carol akan menang atau tidak. Lebih penting bagiku ialah benih kesedaran itu. Biarlah walaupun hanya sedikit, benih kesedaran telah tumbuh dalam bayang di balik mahkota dirinya sendiri. Semangat yang kuharap tidak akan luput, budaya yang kuharap dapat terus diwarisi dan tradisi yang terus dipertahankan. Aku mengatur langkahku meninggalkan dewan KDCA, di celah-celah lautan penonton yang masih hanyut dalam sorak dan tepukan gemuruh.