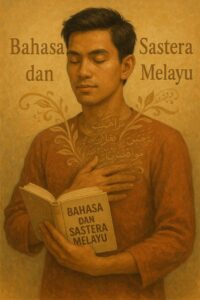KOPI panas yang dihidangkan bersama-sama ubi rebus dan ditabur dengan kelapa parut itu cukup membangkit selera. Amat jarang juadah seumpama itu dapat dijamah di atas meja makan keluarganya. Paling kerap pun masing-masing bersarapan di luar. Dia sendiri sudah lazim menikmati menu makanan segera di restoran yang ditandai dengan huruf M merah yang terpampang tinggi dan megah di tepi lebuh raya.
“Kenapa kau tiba-tiba berminat untuk ambil tahu tentang harta yang sudah lama terkubur itu, Leo?” Sapaan datuknya yang mesra dipanggil aki itu mencantas khayalan singkatnya tadi.
“Kenapa saya berminat? Sebab saya yakin bahawa harta itu benar-benar wujud,” nadanya yakin membalas.
Jawapan itu membuatkan datuk ketawa dan menggeleng-geleng. Ketawa datuk itu kedengarannya ketara dibuat-buat. Dia rasa seperti diperli pun ada atau mungkin perasaannya sahaja yang cepat dicuit rajuk.
“Kenapa? Cerita itu sebenarnya hanya diada-adakan? Harta itu tidak wujud?” Rakus Leo menghambur tanya. Dia tidak puas hati apabila keseriusannya dibalas sambil lewa oleh datuk.
“Orang muda memang pantas membuat rumusan. Sikit-sikit hendak kecil hati, tersinggung! Hanya manusia yang berjiwa besar dan memiliki hati yang cekal saja yang mampu memanggil semula harta itu naik ke atas bumi. Kau ingat tu,” datuk berkata perlahan dan dalam, namun amat terkesan ketegasannya di hujung ayat.
Leo tersipu dalam cuba menyusun bicara dengan teratur nyata dia gagal. Tidak sepatutnya dia bersikap rakus begitu. Dia perlu akur, walaupun keinginannya untuk mengetahui kebenaran di sebalik harta yang terkubur sejak zaman silam itu amat besar, dia perlu menjaga adab, bukan main terjah dan semberono sahaja.
“Pernahkah ada orang kampung yang cuba menggali harta itu, aki?”
Soalan Leo lesap ditelan udara. Sama nasibnya dengan asap kecil dari hujung tembakau daun datuk yang berkepul sesaat dua, kemudian lesap juga.
“Minum dulu kopi yang nenek kau hidang tu. Nenek kau tu pun sudah pandai merajuk kalau makanan yang dia masak lambat dimakan. Ubi rebus tu, kami baru cabut dari kebun petang semalam selepas kau telefon dan beritahu kau mahu balik kampung.” Tenang sahaja balasan datuk.
Persoalan Leo tentang harta yang terkubur, sengaja dilambat-lambatkan rangkaiannya.
Leo mengambil sepotong ubi rebus putih kekuningan yang terhidang lalu isi ubi itu dicecah dengan kelapa parut yang telah digaul dengan sedikit garam. Semasa neneknya membersihkan ubi kayu itu pagi tadi, dia terdengar wanita berusia itu berkata, “Bagus betul hasil tanaman ubi kali ni. Putih kekuningan isinya. Atanok. Kalau isinya putih saja, tidak sedap.”
Sungguh benar kata-kata itu. Dia mengunyah dengan mata terpejam. Puas seleranya! Kopi pekat yang hampir suam diteguk lalu cawannya pun kering dengan sekali hirup. Entahlah, sama ada cawan itu yang saiznya sedang-sedang atau seleranya yang membuak-buak.
“Rajin-rajinlah menjenguk kami di kampung ini. Kita masuk kebun mencabut ubi kayu, boleh kau bawa pulang ke bandar. Petang nanti, tolong nenek kau itu pergi memetik pucuk markisa. Sedap pucuk itu kalau ditumis dengan telur atau dengan ikan bilis mata biru.”
Panjang lebar bicara lelaki yang usianya hampir mencecah 70 tahun itu. Leo hanya mengangguk. Benar kata datuk. Keterlaluan juga jika dia balik kampung semata-mata kerana ingin tahu tentang harta di bawah tanah yang tertanam di kawasan kebun milik datuknya itu.
“Selepas minum, kita pergi ke kedai runcit tepi jalan tu. Kita beli tali tangsi dan mata kail. Esok pagi, kita pergi memancing di bawah pohon buluh perindu yang teduh itu. Itu satu-satunya anak sungai yang masih wujud di kampung kita. Sungai yang lain sudah putus-putus dan tertimbus.”
Leo mengangguk. Dia kenal datuknya. Jika nadanya perlahan dan tegas, ajakan itu pastinya lebih berbentuk arahan.
Matahari sudah terlindung di sebalik pokok-pokok akasia yang berbaris di sepanjang jalan sebelah barat. Jarak kedai runcit yang dimaksudkan dekat sahaja. Peluh tidak sempat pun terbit di bawah ketiak. Terdapat sebuah meja empat segi yang agak besar dan dilengkapi dengan lapan buah kerusi terletak di hadapan kedai runcit itu. Beberapa orang yang hampir sebaya dan lebih muda sedikit berbanding datuk sedang berbalas cerita.
“Manan, kebetulan pula kau muncul ni.” Salah seorang lelaki yang agak berumur di situ mengangkat tangan ke arah datuk dan menggamit agar datuk menghampiri mereka.
Langkah Leo dan datuk terhenti, tidak jadi melangkah masuk ke dalam kedai.
“Mari, kita dengar dulu apa cerita kawan-kawan satu kampung. Mungkin berguna cerita orang-orang kampung tu dengan kau, Leo. Pasang telinga bagus-bagus dan simpan mulut dalam saku,” bisik datuk, tegas.
Kening Leo terjongket sesaat. Apa maksud datuk berkata begitu? Dia mengekor arah datuk melangkah.
Setelah duduk bersebelahan dengan orang yang menggamit mereka tadi, datuk menyalakan daun tembakaunya. Asap kecil berkepul dan teradun bersama udara.
“Manan, kau tolong tengok-tengokkan dulu kawan kita Si Badin. Badan dia makin teruk. Mulanya hanya gatal-gatal, sekarang ni sudah menjadi luka. Ada dia minta kebenaran daripada kau sebelum mula mengorek harta bawah tanah bulan lepas?”
Harta bawah tanah? Pantas Leo menumpukan perhatian.
Kelihatan dahi datuk berkerut sambil mengangguk kecil.
“Ya, Badin dan Ujaris ada meminta kebenaran daripada saya sebelum mula mengorek. Jangan kamu berprasangka buruk pula terhadap saya. Kamu semua sudah maklum, selagi saya hidup, saya pasti memberi kebenaran kepada sesiapa saja yang mahu mencuba kerana saya juga mahu melihat kebenaran kewujudan harta karun itu,” jawab datuk.
“Bukan begitu, Manan. Kami tidak bersangka buruk terhadap kau. Tidak sekali-kali,” balas lelaki tadi sambil menepuk-nepuk perlahan bahu datuk kemudian dia menyambung, “Cuma kalau berkesempatan, mintalah tengok-tengokkan kawan kita tu. Mana tahu, ada cadangan untuk meredakan gatal-gatal yang dialaminya. Kasihan sungguh saya lihat kulitnya yang merah seperti dipanggang.”
Leo mencuri pandang wajah datuk. Mulutnya hampir meluncurkan ayat-ayat tanya tetapi pesanan datuk beberapa minit yang lalu laju mengunci peti suaranya. Pasang telinga, simpan mulut. Leo memujuk perasaan ingin tahunya. Tidak sabar dia mahu bertanya apabila tiba di rumah nanti.
“Selepas makan malam nanti, saya akan pergi melawat Badin. Kalau gatal-gatal yang terkena dengan Badin itu serupa dengan Tuan Markus empat tahun lepas, rasanya saya tahu penawarnya. Janganlah susah hati,” kata datuk.
“Oh, betul! Kalau saya lihat pun, keadaan kulitnya hampir sama dengan apa yang Tuan Markus kena dulu. Tetapi seingat saya, Tuan Markus dulu tidak memenuhi syarat, kan? Ayam jantan berbulu vura itu yang tidak dipenuhi tetapi mereka tetap meneruskan misi. Bukan begitukah?”
“Ada sebab lain yang sukar dijelaskan. Saya sudah pesan, penuhi syarat yang diminta. Kalau tidak, nanti separuh badan lumpuh seperti Tuan Dahlan, dan mata hampir buta seperti Tuan John lapan tahun lalu. Saya bukan mahu menakut-nakutkan. Saya hanya mahu sesiapa yang berminat untuk menggali harta bawah tanah itu, penuhilah syarat yang sudah disebutkan dalam pantang larang yang kita percaya sejak bertahun-tahun dahulu. Jangan main langgar saja.” Panjang lebar datuk meluah kata.
Lelaki tadi mengangguk. Emosi wajahnya yang tegang memperlihatkan garis-garis usianya.
“Tapi jangan bimbanglah. Malam nanti saya pergi melawat Badin,” ujar datuk sambil menepuk-nepuk bahu kawannya itu.
“Leo, mari kita beli tali tangsi dan mata kail, kemudian balik. Malam nanti, mahu lawat Badin yang kurang sihat,” ajak datuk sebelum mengangkat punggung dan masuk ke dalam kedai.
Leo mengekor lagi.
“Kau pasang telinga tadi, kan? Kalau kau mahu tanya, tunggu di rumah,” kata datuk perlahan.
Dengan mulut ternganga, pantas Leo mengangguk. Datuk seolah-olah dapat membaca segala ayat yang sedang berlegar dalam kepalanya.
Leo mundar-mandir di kaki lima berlantaikan bilah-bilah buluh yang sudah diraut halus. Kerap kali anak mata dipicingkan dan kalau boleh, dia mahu pandangannya menerobos pekat malam di hadapan rumah. Selepas makan malam tadi, sebelum pergi melawat Badin, datuk sudah berjanji akan mengulang sekali lagi cerita harta di bawah tanah itu apabila dia balik nanti. Leo sudah mendengar kisah itu banyak kali, sejak dia kecil tetapi malam ini dia mahu mendengarnya sekali lagi.
Dari ruang gelap yang ditenung-tenungnya sejak tadi itu, muncul susuk datuk. Leo lega. Dia menjenguk ke dalam rumah.
“Nek, aki sampai sudah tu,” dia memberitahu.
“Bolehlah kamu menyambung cerita. Kalau hendak kopi beritahu nenek, nenek hantar,” balas nenek dari ruang tengah rumah.
“Hantarlah sekarang. Panjang cerita saya dan Leo malam ni.” Datuk yang sudah memijak anak tangga paling atas terus menyahut.
Leo tersengih suka, dan bertanya, “Apa khabar Badin yang terkena gatal-gatal tu?”
“Kalau dia cepat patuhi arahan yang aki beri tadi, harap-harap cepatlah dia sihat. Dia sudah berterus terang, dia cakap besar. Dia terlalu yakin. Satu lagi yang dia ada terbuat ialah dia tiba-tiba tidak tertahan dan sakit perut. Dekat-dekat pokok buluh perindu itu dia melepas. Itu kurang ajar namanya. Padanlah dia terkena gatal-gatal.”
Datuk melunjurkan kakinya, mencari keselesaan. Dalam masa yang sama, nenek sudah menghantar seteko kopi panas dan dua biji cawan.
“Sembang-sembanglah kamu. Ada tempahan manik lagi perlu disiapkan sebelum hujung bulan ini. Kalau tidak siap, nanti hilang kepercayaan pelanggan dengan kita,” kata nenek sebelum masuk semula ke dalam.
“Terakhir kau mendengar cerita harta yang terkubur di bawah tanah tu semasa kau mahu berpindah ke bandar, bukan? Umur kau ketika itu mungkin 11 tahun.” Kuat betul ingatan datuk.
Leo mengangguk.
“Minum kopi kau supaya kau tidak tertidur,” sambungnya.
Leo akur lagi. Tidak ubah seperti kerbau dicucuk hidung lakunya ketika ini. Kopinya segera dihirup.
“Tidak mengapa. Aki boleh ceritakan sekali lagi. Biar kau betul-betul ingat dan faham. Supaya kau tidak melanggar apa-apa pantang larang.” Keras dan dalam nada itu.
Leo mengangguk dan seratus peratus perhatiannya kini tertumpu kepada datuk.
“Zaman dahulu, terdapat sebuah rumah panjang yang mempunyai lebih kurang 20 buah rumah di dalamnya. Rumah panjang itu dibina di atas tanah ini. Penghuni rumah panjang itu terkenal dengan kebolehan luar biasa mereka menghasilkan gong dan barang-barang perhiasan yang cantik dan tahan lama. Hasil tangan mereka itu sering menjadi pilihan golongan bangsawan. Kebanyakan golongan bangsawan akan membekalkan ketul-ketul emas untuk dilebur dan disadur pada barangan yang mereka tempah. Penghuni rumah panjang itu mengambil kesempatan turut menyadur barangan koleksi mereka sendiri. Maka barangan seperti gong, cerek, pinggan mangkuk, tepak sirih pinang dan perhiasan wanita, segala-galanya bersadur emas.
Satu hari, ketika semua penghuni lelaki keluar berburu dengan diketuai oleh ketua kampung, belum jauh lagi mereka masuk ke dalam hutan, mereka terdengar teriakan dan jeritan dari arah rumah panjang. Mereka pantas berpatah balik namun malangnya hanya pemandangan ngeri dan menyayat hati yang menyambut mereka.
Wanita dan kanak-kanak sudah habis dibunuh. Ramai yang bergelimpangan dan sedang bertarung dengan nyawa yang hampir putus. Darah membasahi lantai rumah panjang. Sayup-sayup mereka lihat kelibat sekumpulan lelaki berkuda dan bersenjata sedang beredar dengan sangat pantas.
Separuh penghuni lelaki dikerah untuk mengejar musuh dan separuh lagi mengebumikan ahli keluarga yang dibunuh. Ketua kampung bersama beberapa orang lelaki yang paling kuat telah menggali lubang yang besar di kedua-dua hujung rumah panjang untuk menanam segala harta benda milik mereka. Lubang-lubang itu ditandakan dengan sumbiling. Setelah segala harta ditanam, ketua kampung pun melafazkan serangkap wasiat berdarah;
Turu tandaha do vura, turu tandaha do lisong.
Turu punan do vura, turu punan do lisong.
Turu vogok dolondom, turu vogok do palang.
Turu roun do tosu, paanahau raha di indi nu om savo nu.
Hondomo no, rahaku om rahanu, miiso.”
Terbelalak mata Leo selepas baris-baris itu dibacakan. Dia ternganga.
“Sekarang kau tahu kenapa Tuan Markus, Tuan Dahlan dan Tuan John berada di dalam penjara? Ketiga-tiga mereka sedang menunggu hari untuk dibicarakan. Hukuman gantung sampai mati sedang menanti mereka. Tetapi kenapa pula Badin tidak dikenakan hukuman yang sama?”
Dengan suara terketar-ketar Leo menjawab, “Sebab Badin tidak menggunakan darah seperti yang diminta. Betulkah begitu?”
Datuk mengangguk. Bibirnya mengherot sinis lalu berkata, “Badin guna darah ayam. Dia tidak memenuhi syarat yang disebutkan dalam wasiat berdarah.”
“Maksudnya Tuan Markus, Tuan Dahlan dan Tuan John sanggup menggunakan darah seperti yang disyaratkan?” Leo bertanya dengan suara yang masih terketar-ketar.
Sesungguhnya dia tidak sangka bahawa harta karun yang terkubur di bawah tanah itu telah mengheret manusia ke lembah hina dan hilang perikemanusiaan. Nafasnya bagai tersekat di kerongkong dan tidak mampu bertanya apa-apa soalan lagi kepada datuk.
“Jadi bagaimana sekarang, Leo? Kau masih berminat mencuba nasib untuk menggali harta bawah tanah itu?”
Dengan lemah Leo mengangkat muka menatap wajah datuk yang nampak tenang menghirup kopi yang semakin kelam asapnya. Sambil menelan air liur yang terasa pahit, Leo menggeleng. Tidak. Dia tidak sanggup. Selepas ini dia tidak akan bertanya walau seinci pun tentang harta karun tersebut.
Titik.
Glosari
Aki – datuk
Atanok – isi ubi yang lembut dan sedap apabila direbus
Dolondom – babi berbulu hitam
Lisong – ayam berbulu hitam
Palang – babi berbulu putih
Raha – darah
Sumbiling – buluh perindu
Vura – ayam berbulu putih