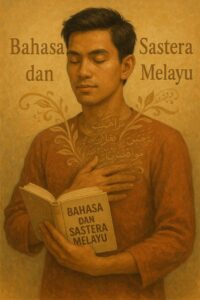RALIT melihat beratus rumpun nenas dengan buah yang hampir sama saiznya membuat Juwita lupa seketika tujuannya ke tempat itu. Ladang yang terbentang itu seakan meraikan ketabahan pokok-pokok itu mengharungi cabaran cuaca yang silih berganti sebelum akhirnya dituai secara berperingkat. Sama tabahnya dengan wanita dalam lingkungan usia 40-an yang sedang berurusan dengan beberapa orang pekerja yang membantunya di ladang itu. Juwita menunggu dengan resah.
“Rehatlah dulu, esok kita bercerita panjang, Juwita mesti penat memandu jauh tadi,” katanya lewat malam tadi seakan mengelak soalan-soalan Juwita.
Dia tidak mendesak walaupun sebenarnya dia tidak penat. Memandu lebih tiga jam walaupun di jalan yang berliku hanyalah terapi minda baginya. Hanya jiwanya yang terlalu letih. Letih memikirkan siapa dirinya dan cinta yang putus di tengah jalan. Pertemuan mereka bukan kebetulan, emak yang mengatur segalanya kerana hanya emak yang mengetahui tempat tersembunyinya rahsia yang selama ini disimpan dengan kemas.
Juwita menutup matanya seketika, menghela nafas kemudian melepaskannya perlahan. Wajah ayah tiba-tiba memenuhi segenap ruang mindanya.
Semuanya bermula apabila Muaz, kekasih hatinya bertandang ke rumah dua bulan yang lepas. Menjalin persahabatan sejak zaman kanak-kanak sehinggalah mereka sama-sama menamatkan pengajian di Institut Pendidikan Guru, Juwita beranggapan bahawa ayahnya tidak akan membantah perhubungan mereka. Dia yakin benar, ayahnya sudah mengenali hati budi Muaz yang sama-sama membesar bersamanya di daerah pergunungan itu. Tekaannya silap.
“Kahwin?” Ayah melenting sebaik Muaz berterus terang menyatakan hasratnya.
Juwita terkedu seketika lalu bergegas meninggalkan ruang tamu apabila melihat wajah ayah yang berubah menjadi tegang. Sayup dari ruang dapur dia mendengar ayah menyebut perkataan adat berulang kali. Nada suaranya begitu padu seolah-olah perkataan itulah yang menjadi kunci persoalan antara mereka. Hanya sesekali kedengaran suara Muaz meningkah. Juwita termangu di meja makan, sesekali jari-jemarinya menjentik teko berisi kopi yang semakin sejuk. Kemudian ketika dia keluar menatang dulang minuman, hanya ayahnya yang duduk tersandar di kusyen, leka menghisap rokok daun kirai. Rupanya Muaz yang pada mulanya begitu bangga kerana datang secara solo untuk melamarnya telah beredar pulang tanpa kata untuknya.
“Ayah?” Juwita kehilangan kata-kata. Tangannya terasa menggigil sehingga hampir terlepas dulang di tangannya.
Ayah langsung tidak mahu memandangnya. Ayah enggan berbicara dengannya selepas itu. Emak pula membisu seribu bahasa. Rumah konkrit bercat ungu di kaki bukit itu menjadi terlalu sunyi. Apa lagi dengan ketiadaan satu-satunya adik perempuannya yang baru sahaja berangkat ke Kuala Lumpur untuk melanjutkan pelajaran. Namun yang lebih memedihkan adalah sikap Muaz yang menjadi dingin tiba-tiba.
Jangankan untuk bersua muka, Muaz memberi pelbagai alasan setiap kali Juwita meminta penjelasan lewat pesanan melalui aplikasi di telefon bimbit. Kiranya lelaki itu turut menyepi daripada hidupnya seperti ibu bapanya yang tampak sibuk membawa hal masing-masing.
‘Jangan berpatah hati hanya kerana orang lain telah kehilangan harapan.’ Juwita memujuk hatinya berkali-kali. Berkali-kali juga dia menyalahkan dirinya tanpa dia mengerti sebabnya.
“Kau tersinggung dengan kata-kata ayah?” Dia menghantar teks pada suatu pagi.
“Kita putuskan saja, Ju. Mungkin tiada jodoh kita,” balas Muaz akhirnya.
“Kenapa? Apa alasannya. Sebab ayah?” soalnya.
Juwita mengulang baca berjela-jela teks pesanan yang dihantarnya selepas itu yang hanya bertanda satu garis dengan jiwa yang semakin kosong. Dia seperti berjalan di suatu padang gersang yang kontang. Namun di kejauhan dia masih melihat pohon-pohon menghijau bagaikan harapan yang belum lagi berakhir.
Kemudian suatu pagi, Juwita mengumpul keberanian untuk berbicara dengan ayah. Dia merayu sungguh-sungguh agar ayah pertimbangkan sekali lagi hasrat yang telah disampaikan Muaz. Tepat dugaannya, pagi yang dingin itu menyaksikan seluruh harapannya berkecai.
“Kalau kamu nak kahwin juga, kahwinlah. Tapi pergi dari sini dan jangan balik-balik lagi,”
“Abang!”
Masih terbayang reaksi spontan emak yang sedang mengacip pinang ketika itu. Wajahnya yang tetap ayu pada usia empat puluhan serta-merta berubah. Dia memandang ayah dengan mata berpinar. Mujur sahaja emak tidak terkacip jari-jarinya yang jelas terketar-ketar menahan marah. Ayah langsung tidak mempedulikan emak.
“Tinggal di langit dengan lelaki itu!” bentak ayah lagi, cawan di tangannya dihentak ke meja makan sehinggakan kopi panas yang baru dituang emak melimpah ke atas permukaan meja kayu tanpa alas itu. “Sejak kecil menyusahkan!”
Kata-kata terakhir ayah memanah hati Juwita bagai petir, petanda akan turunnya hujan yang lebat. Juwita terpempan seketika.
“Ayah halau Juwita?” soalnya perlahan. Suaranya berbaur tangis yang selama ini menjadi rahsia di sebalik tawa dan senyumnya. Itu bukan kali pertama ayah luahkan kata-kata itu. Bezanya, kali ini dia benar-benar dapat merasakan kemarahannya.
“Kau yang menarik diri daripada hidup ayah!” sambut ayah lantas berdiri. “Ayah dah tak kisah. Pergilah! Cari…”
“Abang! Abang marahkan Juwita atau orang lain?” tingkah emak sebelum ayah menghabiskan kata-katanya. Hampir terlepas kacip pinang di tangan kanannya. Sementara tangan kirinya memegang erat pinang yang separuh terkopek kulitnya.
Juwita mengetap bibirnya seakan itulah satu-satunya cara untuk dia melawan gelora rasa di hatinya. Soalan emak menjadi enigma yang menambah rusuh emosinya.
“Siapa orang lain yang emak maksudkan itu?” Juwita meningkah.
Ayah bingkas bangun, menuju ke pintu yang ternganga tanpa menoleh. Mata emak yang basah bergenang air mata mengekori langkahnya kemudian tunduk merenung lantai.
Juwita bungkam. Betapa inginnya dia berlari ke dalam pelukan emak saat itu dan mendengar sesuatu yang boleh meredakan rasa yang membadai di hatinya. Namun seperti biasa itu hanya akan berlaku dalam mimpi. Mungkin benar kata ayah, dia banyak menyusahkan kedua-dua orang tuanya. Betapa jauh bezanya layanan emak padanya berbanding adiknya Juliana yang begitu manja. Juwita tidak ingat kali terakhir dia merasai kehangatan pelukan emak.
“Kenapa, mak?” tanya Juwita akhirnya.
“Bukan hak mak untuk menjelaskannya, Ita. Sepatutnya ayah yang kena berterus terang. Cuma mak mahu kau faham, kita masih hidup dalam lingkungan adat turun-temurun. Pesan nenek moyang, jangan sesekali melanggarnya hanya kerana kamu fikir itu yang terbaik bagi kamu,” kata emak perlahan sambil mencapai tangan Juwita. “Sebenarnya kau dan Muaz tidak boleh berkahwin…”
“Maksud mak?” tanya Juwita kebingungan.
Setahunya dalam adat perkahwinan Dusun, larangan berkahwin hanyalah antara pasangan yang mempunyai pertalian darah. Sedangkan Muaz langsung tidak ada hubungan persaudaraan dengannya. Setahunya juga, sogit atau dendaan untuk kesalahan itu, iaitu beberapa ekor kerbau yang harus dibayar oleh pasangan yang ingin berkahwin bertujuan ‘memutuskan tali persaudaraan’. Itulah adat yang dipanggil pitas dan mesti dipatuhi bagi mengelakkan perkara buruk dalam keturunan di kemudian hari. Namun pilihan terbaik adalah mengelak terjadinya perkahwinan.
“Apa hubungan persaudaraan kita dengan keluarga Muaz, mak?” soalnya, cuak.
“Muaz itu sepupu kau, Juwita.”
Dahi Juwita berkerut, sukar memahaminya.
“Sepupu sekali bagaikan adik-beradik dalam masyarakat kita. Kau terpaksa membuang keluarga sekiranya tetap ingin berkahwin. Itulah maksud ayah apabila dia kata kau berdua kena pindah ke langit…” sambung emak.
Mata mereka bertentang. Lidah Juwita kelu untuk berkata-kata sehinggalah akhirnya emak memberitahu bahawa Juwita bukanlah anak kandungnya.
“Ibu Muaz itu ialah adik ibu kandung kau.”
Pang!
Seakan satu tamparan hinggap di pipinya. Dia benar-benar tidak percaya sehinggalah emak menunjukkan sekeping gambar seorang wanita yang menyerupai wajah emak Muaz mendukung seorang bayi. Dia pasti bayi itu ialah dirinya.
“Di mana ibu?” tanya Juwita akhirnya. Bayang cinta Muaz kian menjauh daripada hidupnya.
“Amboi, termenung panjang, Juwita.”
Juwita tersentak daripada lamunan.
Wajah perempuan yang menyapanya tampak begitu tenang. Nampaknya urusan dengan pekerjanya sudah selesai.
Baru semalam bertemu, namun terasa ada seurat bebenang sutera yang telah mengikat mereka sejak azali membuatkan Juwita terasa seperti begitu dekat di hatinya. Semestinya begitulah kerana yang berdiri di hadapannya ialah ibu kandungnya. Rupanya selama ini emak tahu di mana ibu berada. Barulah dia faham, selama ini emak bersikap dingin padanya kerana dia percaya satu hari nanti Juwita pasti mencari ibu kandungnya walaupun dibantah ayah.
“Kenapa ibu tinggalkan Juwita dan ayah dulu?” Juwita menguji ibu sebaik sahaja mereka berdua melabuhkan punggung menghadap sarapan yang disediakan.
“Mungkin tiada jodoh kami,” jawab ibu selamba.
Juwita terkedu, teringat jawapan Muaz yang sama padanya dulu.
“Ibu yang pilih untuk menarik diri daripada hidup ayah?” Juwita ulangi kata-kata ayah.
Ibu memandangnya sekilas kemudian meletakkan sudu nasi lemak di pinggannya. Tangan kirinya menopang dagu seolah-olah cuba menyusun butir-butir jawapan untuk diucapkan.
“Sebenarnya perkahwinan dengan ayah Juwita adalah pilihan keluarga. Dia suami yang terlalu baik. Ibu pun berusaha menjadi isteri yang baik namun ayah tahu ibu mencintai orang lain. Kami tidak bahagia, mungkin ibu puncanya. Ibulah yang lemah sebab terlalu menurut kata hati. Benar! Ibu menarik diri daripada hidupnya. Dia lepaskan ibu dengan syarat Juwita tidak boleh dibawa bersama,” kata ibu lalu meneguk kopi yang aromanya memenuhi ruang dapur itu.
“Ibu berkahwin dengan lelaki itu?” tanya Juwita tanpa berselindung.
“Tidak. Ibu membawa diri ke daerah ini untuk merawat luka yang orang tak nampak. Sarat dengan rindu pada kamu dan penyesalan yang tak sudah.” Ibu menyusun kata begitu berhati-hati.
“Kenapa? Bukankah dia lelaki yang ibu cintai?”
“Sebab dia sepupu ibu. Ibu bapa kami memberi tentangan hebat. Kami pula ketika cinta membara dulu, tidak mampu membayar sogit untuk putuskan persaudaraan kami mengikut adat seperti yang dipinta oleh keluarga. Masa berlalu, cintanya beralih arah. Ibu juga perlahan-lahan mengerti hikmah di sebalik adat itu, dari sudut agama dan dari sudut perubatan. Juwita carilah maklumat ini nanti.” Panjang lebar ibu terangkan. Matanya berkaca dengan air mata yang ternyata cuba ditahan-tahan.
Perlahan-lahan Juwita menghampirinya, memeluk wanita itu dengan satu perasaan aneh yang selama ini tidak pernah dirasainya. Dia tidak perlukan penjelasan lagi.
Mungkin Muaz dihadirkan dalam hidupnya sekadar asbab menemukan dia dengan ibu atau untuk mengajarnya bahawa hidup jangan sesekali mementingkan diri.
Hidup ini indah jika kita tahu bagaimana untuk menghargainya. Mungkin sahaja perpisahan ibu dengan ayahnya adalah untuk menemukan ayah dengan seseorang yang benar-benar mencintainya, iaitu emak. Ibu hanya belum bertemu jodoh yang sesuai.
“Sebab itukah ibu pilih daerah Pitas ini untuk melarikan diri?” Juwita sekadar bergurau walaupun dia tahu mitos di sebalik nama daerah Pitas yang pernah dibacanya.
“Ha? Sampai ke situ Juwita mencari maklumat?” Ibu seakan terkejut. “Kerana langit yang pernah ibu impikan semakin menjauh, ibu pilih untuk berpijak di bumi yang nyata. Anggap saja sememangnya rezeki ibu di daerah ini,” sambungnya tenang.
Juwita terkedu. Kata-kata ayah pada pagi yang dingin itu berputar dalam ingatannya. Dia tidak pasti sama ada emak telah menceritakan semua yang berlaku antaranya dengan ayah atau hanya sebahagiannya sahaja. Namun dia tahu, luka lama antara ibu dan ayah tidak harus dibiarkan berdarah semula.
“Mari sarapan, kopi dah nak sejuk tu,” ibu memecah keheningan yang mendera jiwa.
Mereka sama-sama tersenyum menampakkan lesung pipit masing-masing yang saling seiras. Juwita mengakui betapa banyak perkara yang berlaku dalam kehidupan kita secara kebetulan. Hanya Allah yang mengetahui hikmah di sebaliknya. Dia bertekad tidak akan mengulangi kesilapan ibunya. Biarlah Muaz cinta pertamanya menemukan seseorang yang terbaik buat dirinya di bawah langit yang sama.
Glosari
Sebutan Pitas berasal daripada perkataan “NOPITAS” atau “MINITAS” yang merujuk kepada definisi “selepas melalui kawasan itu maka orang-orang Bandau terlepas dari kuasa Sindaat Mogkorudu”.